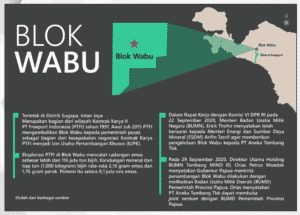Papua No. 1 News Portal | Jubi
Makassar, Jubi – Tim penasihat hukum tujuh tahanan politik atau Tapol Papua yang tengah diadili dalam perkara makar di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur telah membacakan pledoi mereka pada 9, 11, dan 12 Juni 2020. Pledoi itu menyatakan unjukrasa yang terjadi di Jayapura pada 19 dan 29 Agustus 2019 merupakan upaya menuntut penegakan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Hal itu dinyatakan advokat Emanuel Gobay selaku anggota tim penasehat hukum tujuh Tapol Papua. Pledoi itu sekaligus disampaikan sebagai jawaban atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada ketujuh Tapol Papua.
“Secara garis besar, pledoi itu terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya, pendahuluan, [pembahasan] terkait fakta persidangan, dan terkait tuntutan JPU,” kata Emanuel Gobay melalui panggilan teleponnya, Sabtu malam (13/6/2020).
Ketujuh Tapol) Papua itu adalah para mahasiswa dan aktivis yang ditangkap dan diadili pasca gelombang demonstrasi memprotes tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Mereka adalah Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, Ketua KNPB Mimika Steven Itlay, Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Alexander Gobay, serta Feri Bom Kombo, Hengky Hilapok, dan Irwanus Uropmabin.
Baca juga: Bamsoet : Kasus makar (Papua) perlu kehati-hatian
Dalam persidangan yang digelar PN Balikpapan pada 2 Juni 2020 dan 5 Juni 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut ketujuh Tapol Papua itu dengan hukuman penjara antara lima tahun hingga 17 tahun. Buchtar Tabuni dituntut hukuman balik berat, 17 tahun penjara. Sementara Steven Itlay dan Agus Kossay 15 masing-masing dituntut 15 tahun penjara. Alexander Gobay dan Fery Kombo masing-masing dituntut 10 tahun penjara. Sedangkan Irwanus Uropmabin dan Hengky Hilapok masing-masing dituntut hukuman lima tahun penjara.
Menurut Gobay, dalam pendahuluan pledoi itu tim penasehat hukum menjelaskan unjuk rasa mahasiswa dan rakyat Papua di Kota Jayapura pada 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 merupakan reaksi atas ujaran rasisme dan persekusi terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur pada 16-17 Agustus 2019. Tim penasehat hukum menegaskan unjukrasa mahasiswa dan rakyat Papua itu bagian dari upaya menuntut penegakan Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Pledoi itu juga menjelaskan masalah politik antara Papua dan Indonesia, yang hingga kini belum ada titik temunya. Tim penasehat hukum mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dituangkan dalam buku Papua Road Map dan merinci empat akar masalah Papua.”Kami sebutkan penyelesaian persoalan secara hukum dalam konteks ini, hanya menyelesaikan asap, tanpa menyelesaikan [atau memadamkan] baranya,” ujar Gobay.
Baca juga: Surati Jokowi, Pimpinan Lintas Agama se-Papua minta 7 tapol Papua diperlakukan secara adil
Terkait fakta persidangan, kata Gobay, pihaknya menganalisis fakta persidangan dalam setiap perkara. Dalam perkara Buchtar Tabuni misalnya, pledoi itu menegaskan fakta persidangan bahwa Buchtar Tabuni tidak pernah ikut unjuk rasa pada 19 Agutus 2020 maupun pada 29 Agustus 2020. Pledoi itu menyitir kesaksian saksi meringankan yang diajukan tim penasehat hukum, yang menegaskan Buchtar Tabuni tidak mengikuti kedua unjuk rasa itu.
Tim penasehat hukum juga menegaskan bahwa kedua unjuk rasa itu difasilitasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jayapura. Pledoi itu menegaskan bahwa KNPB, ULMWP, maupun Aliansi Mahasiswa Papua bukanlah pihak yang memfasilitasi kedua unjuk rasa di Kota Jayapura itu.
“Berkaitan dengan yel-yel Papua Merdeka, pada prinsipnya [yel] itu sudah lazim disampaikan massa aksi [di Papua]. Yel-yel itu biasa disampaikan dalam unjuk rasa terkait lingkungan hidup, terkait buruh, dan lainnya. Tidak hanya dalam [unjuk rasa mengecam rasisme] itu,” kata Gobay menerangkan pledoi itu.
Pledoi itu menyampaikan keterangan sejumlah saksi ahli yang dihadirkan tim penasehat hukum dalam persidangan, yang menyatakan yel-yel itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi atau ekspresi politik yg dijamin dalam konteks hak asasi manusia. Pledoi itu juga mengutip kembali keterangan saksi ahli psikologi politik yang dihadirkan JPU yang menyatakan hal serupa.
Baca juga: Pemuda Baptis Papua minta tujuh tapol Papua dibebaskan tanpa syarat
“Bisa disimpulkan bahwa itu merupakan ekspresi politik yang dijamin oleh undang-undang. Dari analisis fakta persidangan, kami menilai [unsur] tindak pidana makar tidak terpenuhi dalam unjuk rasa 19 Agustus 2020 dan 29 Agustus 2020,” katanya.
Dalam diskusi daring “Dialog RASISme VS MAKAR” yang diselenggarakan Jubi pada Sabtu (13/6/2020), Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI, Bambang Soesatyo meminta penegak hukum mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan strategis dalam menyelesaikan berbagai dugaan diskriminasi hukum terhadap tujuh Tapol Papua yang diadili di PN Balikpapan. “Pendekatan persuasif, humanis, dan strategis perlu dilakukan agar tidak memicu timbulnya konflik berkelanjutan yang bisa menimbulkan gejolak,” kata Bambang Soesatyo dalam diskusi itu.
Bambang menyatakan pada Agustus lalu terjadi insiden ‘Asrama Papua di Surabaya’ yang berawal dari kesalahpahaman terkait dugaan perusakan bendera merah putih. Karena tidak dikelola dengan baik, insiden tersebut malah memicu timbulnya konflik, yang berujung pada kasus tindakan ujaran rasisme terhadap mahasiswa Papua.
Bambang menyebut adanya kesenjangan penegakan hukum, dengan menyoroti aparatur sipil negara di Surabaya yang melakukan ujaran rasisme dan mendapat vonis lima bulan penjara. Vonis itu dinilai kontras dengan tuntutan bagi para pendemo kasus rasisme Surabaya yang dituntut hukuman hingga belasan tahun penjara dengan tuduhan makar.(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G