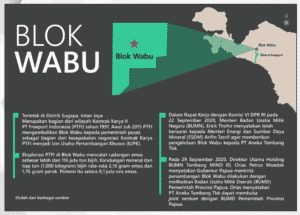Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Para mahasiswa yang berbondong-bondong pulang ke Papua pasca insiden rasisme yang terjadi di Surabaya pada 16 Agustus 2019—atau “mahasiswa eksodus”—menilai hingga kini pemerintah Indonesia tidak berupaya menghapuskan praktik rasisme terhadap orang asli Papua. Hal itu membuat para mahasiswa eksodus enggan melanjutkan kuliahnya di berbagai kota studi di luar Papua.
Hal itu dinyatakan dalam keterangan pers pernyataan sikap mahasiswa eksodus yang disampaikan di Kota Jayapura, Kamis (6/1/2022). Badan Penggurus Posko Umum Exodus Pelajar dan Mahasiswa Papua se-Indonesia Korban Rasisme, Awi Pahabol menyatakan pemerintah justru menghukum para mahasiswa dan aktivis Papua yang menjadi korban rasisme, dan membiarkan praktik rasisme terus berlangsung.
“Pandangan rasis bukan sekedar sentimen anti suatu etnis, melainkan paham atau keyakinan bahwa ras suatu bangsa lebih unggul dari pada bangsa lain. Dengan pandangan itu, bangsa yang kuat [atau merasa superior] melalukan perampasan wilayah secara paksa, dengan kekuatan militer melakukan pemusnahan ras atau etnis suatu bangsa yang dianggap bukan manusia, lemah atau lebih rendah dan terbelakang. Secara ekonomi dan politik, bangsa yang superior akan sangat rasis untuk menindas bangsa inferior,” kata Pahabol.
Baca juga: PBB ingatkan Indonesia terkait penahanan Victor Yeimo
Pahabol menyatakan diskriminasi rasial di Indonesia itu telah termanifestasi dalam praktik bernegara, sehingga Negara telah menjadi alat kekuasaan yang ampuh untuk melakukan penjajahan. Ia menyatakan pandangan rasis terhadap orang Papua sudah tertanam dalam pikiran para pendiri negara sejak mereka berupaya merebut wilayah Papua Barat dari tangan Belanda.
“Pandangan itu didukung kepentingan [eksploitasi] tambang emas di Papua oleh kapitalis Amerika. Kedua kekuatan itu berpandangan bahwa pola hidup dan pola pikir orang Papua terbelakan dan primitif. Implikasinya, muncul sentimen dan prasangka rasial dalam setiap tindakan politik dan militer di Papua Barat,” jelasnya.
Rasisme terhadap orang asli Papua telah menjadi faktor utama pendorong diskriminasi sosial, segregasi dan kekerasan rasial, termasuk genosida terhadap orang Papua. “Berintegarasi ke dalam Indonesia secara paksa dimulai tahun 1961. Masyarakat Papua mengenal wajah Indonesia secara nyata dalam kekerasan dan diskriminasi rasial, dilakukan dengan operasi militer tahun 1969-2000, hingga kekerasan dan pelanggara Hak Asasi Manusia pada masa Otonomi Khusus,” kata Pahabol.
Baca juga: Rakyat Papua akan terus melawan praktik rasisme
Rakyat Papua pun mengalami berbagai bentuk kekerasan rasial. “Rakyat Papua mengalami berbagai bentuk kekerasan rasial berupa pembunuhan, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan dan dikriminasi gender, intimidasi, pembungkaman, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan diskriminasi rasial. Bangsa Papua telah lama mengalami perlakuan rasis secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, penegakan hukum yang diskriminatif, dan pembungkaman ruang demokrasi,” tutur Pahabol.
Ia menegaskan cara pemerintah menangani insiden rasisme di Surabaya dan Malang pada 2019 justru menunjukkan adanya praktik diskriminasi penegakan hukum terhadap orang asli Papua. Banyak orang yang bersuara memprotes insiden rasisme di Surabaya dan Malang namun justru dijadikan tersangka makar, melawan penguasa, dan dipenjarakan.
“Masyarakat Papua diperlakukan berbeda di hadapan hukum. Ada 57 orang Papua dikriminalisasi, ditangkap dan ditahan di berbagai penjara Indonesia. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pembubaran [demonstrasi] secara paksa disertai dengan kekerasan, ujaran-ujaran rasis yang merendahkan harkat dan martabat, penghinaan adat istiadat dan identitas orang Papua. [Di Papua] dibentuk milisi-milisi berdasarkan etnis dan ras, dan di luar Papua [orang asli Papua] diperhadapkan dengan ujaran rasis,” kata Pahabol.
Baca juga: Gustav Kawer sebut demokrasi mati dan rasisme merajalela
Alih-alih melakukan upaya serius untuk menghapuskan praktik rasisme, pemerintah dinilai justru lebih sibuk berupaya memisahkan persoalan rasisme terhadap orang asli Papua dari isu politik Papua. Pahabol juga menilai para pelaku ujaran rasisme di Surabaya justru dihukum ringan, sementara para mahasiswa dan aktivis Papua yang memrpotes rasisme justru dihukum lebih berat.
Ketika unjuk rasa memprotes insiden rasisme di Surabaya meluas di berbagai wilayah di Tanah Papua, Presiden Joko Widodo justru memilih menambah pasukan TNI/Polri di Papua. “Pemerintah juga melakukan kekerasan dengan membatasi ruang gerak demokrasi, menutup jalur komunikasi dan jaringan internet di sebagian besar wilayah Papua sejak tanggal 21 Agustus 2019. Hal ini mencerminkan pendekatan negara yang represif, masif, dan militeristik dalam menyikapi tuntutan rakyat Papua atas ketidakadilan yang terjadi di Papua,” kata Pahabol.
Ia menjelaskan insiden rasisme di Surabaya serta cara pemerintah merespon insiden itulah yang memicu ribuan mahasiswa asal Papua yang berkuliah di luar Papua untuk pulang. Mereka tidak lagi merasa nyaman melanjutkan pendidikan mereka di luar Papua. Pahabol menyatakan ada sekitar 6.000 mahasiswa yang tengah menumpuh pendidikan di berbagai kota studi di luar Papua yang memilih pulang pasca insiden rasisme di Surabaya.
Baca juga: Menginjak kepala dan pandemi rasisme yang belum berujung
“Di balik [itu semua], [penyebab] eksodus itu tidak lepas dari adanya tindakan teror dan intimidasi yang dirasakan, ketidaknyamanan [kami muncul] setiap [terjadi] pergolakan di Papua dalam bentuk aksi besar. Maklumat Majelis Rakyat Papua dan tanggapan Gubernur Papua [saat itu menyatakan jika] pelajar dan mahasiswa Papua di luar Papua tidak merasa aman di kota studi masing-masing, agar segera balik ke Papua. Setelah di Papua, mahasiswa eksodus melakukan aksi protes bersama mahasiswa di Papua dan masyarakat Papua untuk melawan ketidakadilan terhadap manusia Papua. Sampai saat ini, mahasiswa eksodus yang masih bertahan adalah murni korban perlakuan teror dan intimidasi di seluruh kota studi, dan bagian dari penangkapan enam aktivis mahasiswa Papua di Jakarta,” kata Pahabol.
Salah satu unjuk rasa anti rasisme dilakukan para mahasiswa eksodus di Kota Jayapura pada 23 September 2019. Pahabol menyatakan polisi membubarkan paksa para mahasiswa eksodus yang ada di Expo Waena, hingga empat orang mahasiswa tertembak.
“Gubernur Papua, DPR Papua dan MRP segera mengusut tuntas empat korban massa aksi [mahasiswa eksodus] di Expo Waena pada 23 September 2019, empat korban jiwa meninggal dunia, atas nama Otier Wenda, Yeri Murib, Azon Mujijau,dan Yermanus Wesareak. Tidak kurang dari 700-an massa aksi mengalami kekerasan fisik oleh aparat keamanan. Kasus tersebut merupakan tindakan pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan secara adil lewat jalur hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Pahabol.
Baca juga: Yan Mandenas: Insiden Merauke, berindikasi melanggengkan rasisme
Aktivis Hak Asasi Manusia, Haris Azhar yang turut hadir dalam keterangan pers itu menyatakan tidak ada yang berubah dalam cara penanganan masalah Papua pasca insiden rasial di Surabaya dan Malang pada 2019. Praktik kekerasan di Papua masih sama dan punya relasi yang kuat dengan kepentingan bisnis di Papua.
“Praktik kekerasan itu memang disengaja untuk menciptakan [rasa] frustrasi dan ketakutan orang asli Papua untuk bersuara, takut untuk bertindak secara hukum. Jadi, seolah-olah dibuat frustasi menjalani proses formal atau proses hukum yang bertele-tele,” jelasnya.
Haris menyoroti bahwa pemerintah justru semakin menambah jumlah aparat keamanan di Papua. “Hal itu dilakukan di daerah-daerah yang diduga mengandung sumber daya alam,” kata Haris.
Hapus pasal makar
Selain menyatakan tidak akan kembali ke kota studi masing-masing, para mahasiswa eksodus yang masih bertahan di Papua juga meminta Gubernur Papua menetapkan tanggal 16 Agustus sebagai Hari Anti Rasisme di Tanah Papua. Mereka juga meminta para pemangku kepentingan politik di Papua segera membebaskan para mahasiswa dan aktivis yang masih menjalani proses hukum karena melakukan unjuk rasa anti rasisme Papua.
“Kami menuntut pencabutan pasal makar yang menindas dan mengkriminalisasi setiap orang asli Papua. Pemerintah Indonesia dan Kapolda Papua [harus] segera membebaskan Victor Yeimo tanpa syarat. Beliau bukan pelaku rasis, melainkan korban rasis dan kriminalisasi hukum Indonesia yang juga berlaku rasis,” kata Pahabol.
Para mahasiswa eksodus juga meminta Presiden Joko Widodo menarik semua pasukan organik dan non organik dari Tanah Papua, dan menyelesaikan masalah banyaknya warga sipil yang mengungsi karena konflik di Maybrat, Nduga, Intan Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. “PBB dan Indonesia [harus] segera memberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua untuk membebaskan [kami] dari segala bentuk penindasan rasisme, kolonialisme, dan kapitalisme,” kata Pahabol. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G