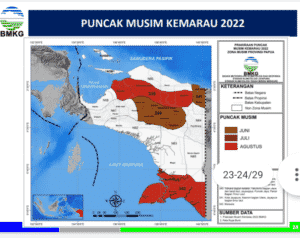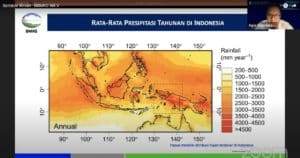Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Kerusakan hutan adat suku Awyu di Kabupaten Boven Digoel, Papua diabadikan dalam film dokumenter berjudul “The Awyu” yang diproduksi The Gecko Project. Selain itu, komunitas Papuan Voice juga membuat film dokumenter tentang hutan masyarakat berjudul “Mama Mariode”, yang mengisahkan perjuangan seorang mama di Sorong, Papua Barat untuk mempertahankan hutan adat.
Kedua film yang menyoroti persoalan hutan ulayat masyarakat adat di Tanah Papua itu telah diputar dan diskusikan di Kota Jayapura, Papua, pada Rabu (17/2/2021), untuk menggalang kesadaran orang asli Papua (OAP) terhadap kondisi hutan adat dan sumber daya alamnya. Hutan adat dan sumber daya alam mereka terus dikeruk demi kepentingan korporasi besar.
Koordinator Umum Papuan Voices, Bernard Koten mengatakan film The Awyu bercerita tentang kerusakan hutan adat milik suku Awyu, Boven Digoel, Papua. Sedangkan film Mama Mariode berkisah tentang seorang mama Sorong, Papua Barat. “Hutan masyarakat adat dicaplok. Film The Awyu jadi pembuka diskusi dan nonton bersama Papuan Voices,” kata Koten saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Sabtu (20/2/2021).
Baca juga: Papuan Voices gelar Festival Film Mini tentang masyarakat adat dan SDA Papua
Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, Yuliana Langowuyo mengatakan dengan menonton kedua film ituorang Papua dapat mengetahui kondisi lingkungan dan sumber daya alamnya. “Biasanya masyarakat baru sadar setelah masalah terjadi. Mulai ada perkelahian, baru sadar menjadi korban investasi. Perusahaan, setelah ambil barang, dong pergi, masyarakat tetap saja begitu,” kata Langowuyo.
Ia menyatakan biasanya investor masuk ke Tanah Papua dengan menawarkan janji yang bagus. Perusahaan akan menunjukkan rencana pembuatan jalan, serta rencana pembangunan lainnya, lalu diam-diam mendekati orang tertentu untuk membuat surat pelepasan hak atas tanah ulayat.
Film The Awyu mengisahkan tentang masuknya sebuah perusahaan, serta kisah pilu masyarakat adat Awyu mengalami dampak dari aktivitas perusahaan yang beroperasi di atas tanah adatnya. Salah satu peserta diskusi, Fr Raymondus membagikan pengalamannya sebelum masuk seminari (sekolah pendidikan imam Katolik), saat ia bekerja di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Baca juga: Bagaimana Boven Digoel menjadi sasaran perkebunan sawit terluas di dunia.
“Dekat dengan bapak Stefanus (tokoh dalam film) yang punya lahan. [Beliau] sempat tanya tentang pengolahan kayu ketika perusahaan membongkar hutan. [Apakah perusahaan akan] hitung [setiap] kayu [yang ditebang] atau tidak, [apakah kayu itu dihitung] per [luasan] lahan atau per kubik [kayu yang ditebang]?. Tetapi dibilang, yang ukuran besar saja yang dihitung, sedangkan ke bawah tidak dihitung untuk diganti rugi kepada pihak [pemilih hak ulayat] tanah,” kata Raymondus.
Pendapat serupa dikatakan film maker dan aktivis lingkungan, Roberto Yekwam. Dia mengatakan, perusahaan sawit mulai melirik hutan masyarakat adat di Tambrauw, Papua Barat. “Masyarakat sempat melakukan penolakan besar-besaran, karena masyarakat adat memperkirakan akan ada dampak yang besar dengan hadirnya perusahaan tersebut di lembah Kebar,” ujar Yekwam.
Yekwam menyatakan dirinya prihatin dengan praktik penerbitan izin perkebunan yang tidak melibatkan masyarakat adat selaku pemilih hak ulayat. Praktik itu menimbulkan konflik tenurial antara masyarakat adat dan perusahaan, bahkan menimbulkan konflik antara kelompok masyarakat adat dengan kelompok masyarakat adat yang lain. “Saya berharap bahwa pemerintah di Papua dan Papua Barat bisa serius menjaga hutan tropis dan memberdayakan masyarakat untuk mengelola [hutan] secara berkelanjutan dan lestari,” katanya.
Baca juga: Dana publik pemerintah Korea Selatan ikut mendorong deforestasi Papua
Sebelumnya, Koalisi Indonesia Memantau menyatakan dalam 20 tahun terakhir, luasan hutan di Papua telah berkurang 663.443 hektare. Deforestasi tahunan selama 20 tahun terakhir mencapai rata-rata 34.918 hektare. Dari 663.443 hektare deforestasi yang terjadi di Tanah Papua, sejumlah 71 persen diantaranya terjadi pada kurun waktu 2011 – 2019. Puncak deforestasi Tanah Papua terjadi pada 2015, dengan pembukaan kawasan hutan yang mencapai 89.881 hektar.
Pada era Kementerian Kehutanan dipimpin oleh Malem Sambat Kaban (2005-2009), deforestasi di Tanah Papua mencapai luasan 102.416 hektare. Pada masa kepemimpinan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (2010-2014), deforestasi di Tanah Papua mencapai 198.217 hektare.
Koalisi Indonesia Memantau menyebutkan bahwa terdapat 72 SK Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) di Tanah Papua seluas 1.569.702 hektare, yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dalam periode 1992-2019. Tujuan utamanya untuk perkebunan kelapa sawit dengan luas 1.308.607 hektare. Data itu membuat Koalisi Indonesia Memantau khawatir bahwa deforestasi di Tanah Papua akan terus berlanjut.
Direktur Auriga, Dedy P Sukmara dalam presentasinya mengatakan secara umum tren deforestasi Indonesia memang cenderung menurun. Akan tetapi, di sepuluh provinsi yang kaya akan hutan, angka deforestasi cenderung tetap, bahkan naik sejak 2011. Di Riau dan Jambi misalnya, angka deforestasi tetap tinggi. “Kami melihat Tanah Papua yang paling rentan terjadi deforestasi,” katanya. (*)
Ralat: Berita ini mengalami perbaikan. Dalam publikasi awal tertulis “Kerusakan hutan adat suku Awyu di Kabupaten Boven Digoel, Papua diabadikan dalam film dokumenter berjudul “The Awyu” yang dibuat komunitas Papuan Voice. Komunitas yang sama juga membuat film dokumenter “Mama Mariode”, yang mengisahkan perjuangan seorang mama di Sorong, Papua Barat untuk mempertahankan hutan adat.” Pada Sabtu (20/2/2021) pukul 23.02 WP, informasi itu diperbaiki menjadi “Kerusakan hutan adat suku Awyu di Kabupaten Boven Digoel, Papua diabadikan dalam film dokumenter berjudul “The Awyu” yang diproduksi The Gecko Project. Selain itu, komunitas Papuan Voice juga membuat film dokumenter tentang hutan masyarakat berjudul “Mama Mariode”, yang mengisahkan perjuangan seorang mama di Sorong, Papua Barat untuk mempertahankan hutan adat.” Redaksi meminta maaf atas kesalahan tersebut.
Editor: Aryo Wisanggeni G