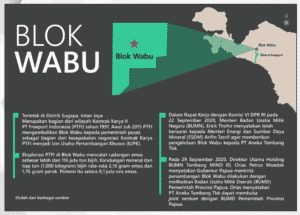Papua No. 1 News Portal | Jubi
Makassar, Jubi – Jurnalis senior Papua, Victor C Mambor menyatakan cara pandang media terhadap Papua mesti diubah.
Ia mengatakan, dalam pemberitaan tentang Papua selama ini, media lokal maupun media nasional hanya cenderung menyoroti daerah konflik. Akibatnya para pihak yang berkonflik terlibat ‘perang media’. Saling berbalas-balasan tanggapan lewat pemberitaan media.
Pernyataan itu dikatakan Victor C Mambor alam diskusi daring Papua Strategic Policy Forum #5 “Urgensi Pembentukan Pengadilan HAM & Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua” pada Senin (20/7/2020).
Diskusi yang digelar Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada (UGM) ini menghadirkan beberapa pembicara.
Mereka adalah Anum Siregar (Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua), Beka Ulung Hapsara (Komisioner Komnas HAM RI), Michael Manufandu (Tokoh Papua/Duta Besar senior), dan Gabriel Lele (Peneliti Gugus Tugas Papua UGM).
“Kita tidak bisa meletakkan konflik ini sebagai bahan diskusi bersama. Ini mesti dibenahi di Papua,” kata Victor Mambor.
Menurutnya, perusahaan media di Papua juga mesti berbenah. Hingga kini sedikitnya ada 54 media online di Papua, namun hanya lima perusahaan pers di Papua dan Papua Barat yang memenuhi standar ketentuan Dewan Pers, di luar lembaga penyiaran publik TVRI, RRI, dan Kantor Berita Antara.
Perusahaan media itu, yakni Cenderawasih Pos, Jubi, Harian Pagi Papua (tidak terbit cetak lagi), Bisnis Papua (tidak terbit cetak lagi), dan Radar Sorong (Papua Barat).
Kondisi ini menyebabkan munculnya praktik jurnalis yang tidak lagi berpegang pada etika keberimbangan, independen dan profesional.
“Bagaimana kita berharap pada peran media kalau iklim perusahaan pers tidak sehat. Nanti ada uang baru jadi berita. Bagaimana masyarakat di kampung-kampung yang tidak memiliki uang. Mereka tidak bisa menyampaikan informasi yang bisa dikonsumsi publik,” ujarnya.
Masalah lain, masih sering terjadi kekerasan terhadap jurnalis di Papua, baik verbal maupun fisik. Korbannya terutama wartawan asli Papua.
Dalam pemberitaan media, juga sangat minim laporan indepth dan investigasi. Misalnya saat demontrasi antirasisme, yang meluas menjadi rusuh di Wamena, Jayawijaya pada September 2019 lalu.
Hampir semua media hanya memberitakan pernyataan para pejabat publik dan menempatkan mayoritas korban adalah warga perantau.
“Selain itu, hoaks, disinformasi soal Papua, adanya website siluman masih terjadi [hingga kini]. Hal-hal ini perlu dibenahi kalau mau melibatkan media menyelesaikan konflik,” ucapnya.
Menurut Mambor, hingga kini akses jurnalis asing ke Papua juga masih dibatasi. Padahal jurnalis asing diharapkan dapat memberikan perspektif lain mengenai Papua.
Kini media atau jurnalis nasional dan lokal hanya berkutat pada cara pandang NKRI harga mati dan Papua Merdeka. Cara pandang itu mengakibatkan munculnya tafsir lain oleh publik.
“Saya yakin kesalahan kebijakan pemerintah pusat terhadap Papua, karena informasi yang salah. Ibarat obat yang diberikan, tidak sesuai dengan jenis penyakit,” ujarnya.
Tokoh Papua, Michael Manufandu mengatakan memori trauma yang terekam dalam ingatan orang asli Papua, lahir dari latar belakang sejarah sejak Orde Baru hingga kini.
Trauma itu diceritakan turun temurun dari setiap generasi. Mestinya ini dapat dijawab dengan baik, dan dibutuhkan peran media untuk itu. Akan tetapi apa yang diharapkan dari media belum sepenuhnya terwujud.
“Pers kita memang tidak bisa menjadi pembanding. Makanya Peran pers juga penting agar bisa mengimbangi ingatan yang lahir dari ingatan kolektif itu,” kata Manufandu.
Katanya, seiring perkembangan terkini, generasi baru Papua yang lahir dan dididik secara baik, justru tetap menentang dan melawan Pemerintah Indonesia. Masih ada anggapan kolonialisme, kapitalis dan militeristik terhadap negara.
“Ini yang menjadi pertanyaan. Ada kesan ketidak saling percaya antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat Papua dan masyarakat luar Papua,” ucapnya.
Menurutnya, situasi ini memunculkan stigma politik terhadap orang asli Papua, yang disebut separatis. Berbagai prasangka inilah yang mesti dibicarakan dan mencari solusinya. (*)
Editor: Edho Sinaga