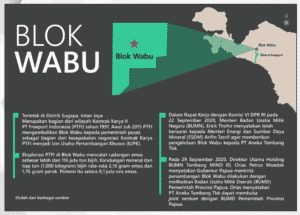Papua No. 1 News Portal | Jubi
Makassar, Jubi – Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan adanya bendera Bintang Kejora atau atribut Papua merdeka, serta permintaan penentuan nasib sendiri atau referendum dalam unjuk rasa mengecam ujaran rasisme di Kota Jayapura, 29 Agustus 2019 lalu sebagai bentuk protes orang asli Papua (OAP) terhadap ketidakadilan yang mereka alami selama ini.
Pernyataan itu dikatakan Laurenzus Kadepa melalui panggilan teleponnya, Rabu (27/5/2020).
Menurutnya, hal itu juga ia sampaikan ketika untuk kedua kalinya diminta penasihat hukum terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi meringankan untuk Hengki Hilapok, dalam sidang lanjutan melalui telekonferensi pada Selasa (26/5/2020).
Hengki Hilapok merupakan satu di antara tujuh tahanan politik atau Tapol Papua yang didakwa pasal makar terkait unjuk rasa mengecam ujaran rasisme di Kota Jayapura pada 29 Agustus 2019 lalu. Hilapok bersama enam tapol Papua lainnya kini dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Balikpapan, Kalimantan Timur.
“Dalam keterangan saya, saya menyampaikan kepada hakim bahwa adanya atribut Papua Merdeka, [tuntutan] penentuan nasib sendiri [atau] referendum adalah bentuk kemarahan atas perlakuan ketidakadilan oleh oknum negara, dan perlakuan rasis terhadap orang Papua berkali-kali. Puncaknya pada 19 dan 29 Agustus 2019. Hampir seluruh kota di Papua dan Papua Barat melakukan aksi,” kata Kadepa.
Katanya, unjuk rasa di berbagai daerah di Papua dan Papua Barat itu dipicu ujaran rasisme oleh sekelompok orang yang mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur beberapa hari sebelumnya.
Beberapa oknum aparat keamanan di lokasi, juga diduga mengucapkan kata-kata rasisme kepada penghuni asrama, yang dituduh membuang bendera Merah Putih yang dipasang di depan asrama ke saluran air.
Peristiwa itu kemudian memicu reaksi warga Papua. Ribuan rakyat Papua turun jalan melakukan aksi protes. Di Kota Jayapura unjuk rasa mengecam ujaran rasisme berlangsung pada 19 dan 29 Agustus 2020.
Akan tetapi unjuk rasa terakhir meluas menjadi rusuh dan menyebabkan puluhan orang ditangkap. Sebanyak tujuh orang diantaranya didakwa pasal makar dan kini dititipkan di rumah tahanan Balikpapan, Kalimantan Timur.
Dalam keterangannya sebagai saksi meringankan, Kadepa juga menyatakan unjuk rasa menolak (mengecam) ujaran rasisme saat kejadian Surabaya di Jayapura pada 19 dan 29 Agustus 2019, merupakan aksi spontanitas masyarakat Papua. Aksi itu dikoordinir mahasiswa dibantu beberapa organisasi, di antaranya [Kelompok] Cipayung seperti PMKRI, HMI dan lainnya.
“Saya bilang, tidak ada keterlibatan organisasi KNPB, ULMWP, AMP, dan TPN/OPM dalam aksi itu. Keterlibatan mahasiswa dalam aksi mengecam ujaran rasisme bertujuan agar aksi berjalan baik,” ujarnya.
Katanya, kalaupun unjuk rasa 29 Agustus 2019 di Kota Jayapura meluas menjadi rusuh, situasi itu diluar kehendak mahasiswa. Mahasiswa tidak memerintahkan melakukan pembakaran, perusakan dan pembunuhan atau kekerasan lainnya.
Ia berpendapat, jika mahasiswa tidak mengawal unjuk rasa di Kota Jayapura saat itu, akibatnya justru bisa lebih parah lagi. Mestinya peran mahasiswa mengendalikan pengunjukrasa dalam aksi itu dihargai, bukan justru disalahkan.
“Saya menyampaikan kepada majelis hakim, tujuh tapol Papua yang didakwa pasal makar hanyalah korban, sehingga saya meminta majelis hakim bijak dalam memutuskan perkara ini,” ucapnya.
Penasihat hukum atau PH tujuh terdakwa makar Papua menilai, proses persidangan secara telekonferensi berpotensi melanggar hak-hak para terdakwa.
Satu di antara PH terdakwa, Emanuel Gobay mengatakan persidangan secara telekonferensi tidak efektif dan dapat berdampak pada pelanggaran hak-hak tersangka yang dijamin dalam Undang-Undang (UU) nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Misalnya ketika penyampaian saksi atau keterangan terdakwa saat membantah keterangan [saksi] ahli, jika suaranya tidak jelas, bisa berpengaruh pada penilaian hakim. Bisa saja hakim menyimpulkan berbeda atau multi tafsir,” kata Emanuel Gobay kepada Jubi belum lama ini.
Menurutnya, ketika persidangan telekonferensi, PH sulit membatasi ketika saksi ahli yang memberikan keterangan tak sesuai bidangnya, karena para pihak berbicara dari tempat berbeda dan tidak langsung berada di depan majelis hakim. (*)
Editor: Edho Sinaga