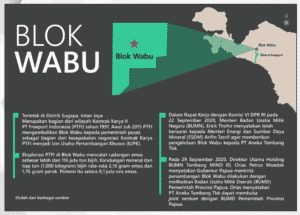Papua No.1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Pemerintah Indonesia didesak mencabut tuduhan makar dan membebaskan tanpa syarat seorang aktivis yang ditahan karena mendukung kemerdekaan Papua Barat secara damai
Organisasi Human Rights Watch dalam rilisnya yang diterima Jubi hari ini mengatakan, Presiden Joko Widodo juga perlu memerintahkan polisi dan militer Indonesia, yang terlibat dalam operasi keamanan di Papua dan Papua Barat, untuk tidak melanggar dan menghormati hak asasi manusia, sesuai dengan hukum internasional.
Seperti diberitakan sebelumnya, 9 Mei 2021, Satgas Nemangkawi menangkap Victor Yeimo, juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jayapura, Papua. Polisi menuduhnya melakukan “tindakan makar” atas berbagai pernyataan yang dia sampaikan pada 2019 saat protes anti-rasisme dan kerusuhan yang mengikutinya di Papua dan Papua Barat, serta minta referendum kemerdekaan.
Kepala Kepolisian Daerah Papua Mathius Fakhiri mengatakan bahwa polisi masih menggali kasus-kasus yang menimpa Yeimo,
“Biar saja dia sampai tua di penjara,” katanya.
Di sisi lain, Brad Adams, direktur Asia dari Human Rights Watch mengatakan Kepolisian Indonesia sudah semestinya menyelidiki berbagai kekerasan mematikan dan pembakaran di Papua pada 2019, namun jangan kejadian tersebut dijadikan dalih untuk menindas para aktivis yang bekerja secara damai.
“Investigasi independen masih diperlukan terhadap peran pasukan keamanan, dan pihak berwenang perlu menuntut mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran,” ujarnya.
Selama lima dekade, pemerintah Indonesia diskriminasi masyarakat asli Melanesia di daerah yang kaya akan sumber daya dan terpencil di Papua dan Papua Barat, kata Human Rights Watch.
Yeimo, 38 tahun, seorang penulis dan aktivis terkemuka yang ikut mendirikan KNPB setelah penembakan terhadap Opinus Tabuni, warga Papua yang merayakan Hari Masyarakat Adat Internasional pada 9 Agustus 2008. Tak ada orang yang ditangkap atas pembunuhan tersebut.
Yeimo dan beberapa pendiri KNPB ditangkap pada 2008 dan 2009 karena advokasi referendum kemerdekaan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa di Papua dan Papua Barat.
Di laman Facebook-nya, Yeimo berulang kali menulis tentang rasisme terhadap orang Papua dan menyerukan perundingan antara gerakan kemerdekaan Papua Barat dan pemerintah Indonesia. Ia beberapa kali bicara di berbagai forum di Indonesia dan internasional tentang masalah lingkungan dan hak asasi manusia Papua.
Pada Agustus 2019, puluhan ribu warga Papua ikut aksi damai di setidaknya 30 kota di Indonesia sebagai reaksi atas serangan rasis oleh militan dan tentara Indonesia di sebuah asrama mahasiswa Papua Barat di Surabaya. Video menunjukkan beberapa tentara Indonesia berulang kali menggedor pagar asrama sambil meneriakkan kata “monyet”.
Polisi menembakkan gas air mata ke dalam asrama dan menangkap puluhan mahasiswa Papua. Video tersebut beredar luas dan memicu protes, termasuk penjarahan dan pembakaran di Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Wamena.
Sekurangnya 43 pemimpin aksi Papua dan aktivis KNPB didakwa dengan makar dan dijatuhi hukuman meskipun mereka tidak terlibat dalam kekerasan pada 2019. Salah satunya Surya Anta Ginting, koordinator Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat, yang divonis bersama lima aktivis Papua lainnya, pada April 2020. Mereka dijatuhi hukuman antara delapan hingga sembilan bulan penjara.
Di Balikpapan, tujuh aktivis KNPB dan tokoh mahasiswa Papua dijatuhi hukuman antara 10 dan 11 bulan penjara dengan pasal makar pada Juni 2020. Di antaranya Buchtar Tabuni, salah satu pendiri KNPB, dan Agus Kossay, Ketua KNPB, yang dipenjara atas sikap pro-kemerdekaan mereka.
Kepolisian waktu itu memasukkan Yeimo, yang banyak bicara kepada media internasional, dalam daftar “buronan” mereka, meski polisi tak mengambil tindakan lebih lanjut.
Human Rights Watch tidak mengambil posisi atas klaim masyarakat Papua atas penentuan nasib sendiri, namun mendukung hak setiap orang, termasuk pendukung kemerdekaan, untuk mengekspresikan aspirasi politik mereka secara damai tanpa takut ditangkap atau bentuk pembalasan lainnya.
Penangkapan Yeimo pada 9 Mei terjadi ketika operasi militer Indonesia di Papua meningkat sebagai reaksi atas pembunuhan pada 25 April dalam penyergapan terhadap Brigadir Jenderal I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, seorang perwira Kopassus, di Pegunungan Tengah.
Nugraha adalah jenderal pertama yang tewas selama lima dekade konflik intensitas rendah di Papua. Yeimo menyebut kematian Jenderal Danny Nugraha sebagai “tumbal” keengganan pemerintah dan parlemen Indonesia dalam mencari solusi politik di Papua.
Presiden Jokowi menanggapi pembunuhan tersebut dengan memerintahkan militer dan polisi untuk memburu dan menangkap setiap orang yang bertanggung jawab atas kematian tersebut. Pemerintahan Jokowi lantas menyatakan “kelompok kriminal bersenjata” –tanpa disebutkan namanya– sebagai organisasi teroris, yang tampaknya mengacu pada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
Kepolisian Indonesia memberangkatkan 12 kompi tambahan (sekitar 1.200 orang) dari Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, sementara TNI mengirimkan 400 tentara Batalyon 315/Garuda dari Bogor, dekat Jakarta.
Beberapa organisasi hak asasi manusia di Indonesia menyatakan keprihatinan bahwa pemerintah memberi label kelompok bersenjata ini “teroris” karena ia dapat mendorong pelanggaran lebih serius dari oleh pasukan keamanan Indonesia di Papua.
“Perlawanan orang Papua terhadap negara Indonesia serta penindasan secara militer dan polisional sering kali ditanggapi dengan pelanggaran lebih banyak. Pihak berwenang Indonesia harus memastikan bahwa semua operasi keamanan di Papua dilaksanakan sesuai hukum dan bahwa aktivis damai dan warga sipil lainnya tidak menjadi sasaran,” kata Adams. (*)
Editor: Edho Sinaga