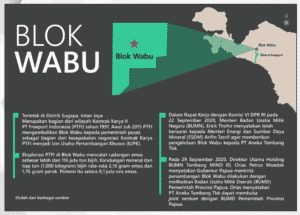Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Tahun 2019 setelah menerbitkan Buku Seri Memoria Passionis “Papua Bukan Tanah Kosong: Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia di Tanah Papua 2018”, Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC FP) tahun ini kembali menerbitkan buku tentang pengakuan harkat dan martabat manusia Papua dalam kasus rasisme di Tahun 2019. Buku ini merekam rentetan peristiwa seputar kasus rasisme terhadap kemanusiaan Papua yang cukup menyita perhatian publik di Tanah Papua maupun di luar Papua hingga tahun 2020 ini.
Bermula dari tindakan rasisme dan penghinaan terhadap kemanusiaan Papua, 15 Agustus 2019 lalu, kisah kelam tentang Papua kembali dihadirkan. Manusia dan kemanusiaan Papua menjadi sasaran para pihak yang berslogan ‘harga mati’ untuk keutuhan sebuah negara. Pelbagai kisah kelam ini coba direkam dan dituliskan dengan lebih rinci oleh salah satu pemerhati persoalan Papua yang adalah sesepuh SKPKC Fransiskan Papua, Theo van den Broek.
“Buku tersebut saya tulis karena banyak pertanyaan dari publik di luar Papua setelah mendengar ada demonstrasi besar yang terjadi saat itu. Awalnya saya menulisnya dalam bahasa Belanda lalu saya kirimkan kepada keluarga dan kawan-kawan saya di Belanda. Mereka bertanya, apakah tulisan saya itu bisa dipublikasikan atau tidak? Namun saya tidak berminat mempublikasikannya di Belanda,” ungkap Theo kepada Jubi, Senin (25/8/2020) mengenai buku “Tuntut Martabat, Orang Papua Dihukum: Seri Memoria Passionis No.38” yang ditulisnya.
Tapi kemudian, pemerhati persoalan Papua ini berpikir bahwa publik di Indonesia perlu mendapatkan informasi yang benar terkait peristiwa yang terjadi pada Agustus – September tahun lalu itu. Ia lalu mulai menuliskannya dalam bahasa Indonesia dan memberikan catatan kaki untuk memperjelas informasi yang ia tuliskan dalam buku tersebut.
“Sejak awal saya mendapatkan kesan bahwa peristiwa rasialisme di Surabaya tanggal 16 Agustus itu adalah perbuatan yang disengaja. Karena sebelumnya peristiwa yang sama telah terjadi beberapa kali. Sehingga membuat kemarahan besar di Papua,” lanjut Theo.
Anehnya, lanjut Theo, peristiwa yang terjadi bukan hanya di Surabaya namun juga di Malang dan Semarang itu direspon oleh pemerintah Indonesia sebagai peristiwa biasa. Bahkan dianggap sebagai hoax. Penyangkalan ini menurutnya, membuat publik Indonesia hanya tahu bahwa apa yang terjadi di Papua sebagai respon atas peristiwa di Surabaya, Malang dan Semarang itu sebagai aksi kelompok separatis.
Publik Indonesia, menurutnya terus menerus diarahkan oleh media di Indonesia untuk mempercayai penyangkalan tersebut sehingga respon pemerintah atas reaksi rakyat Papua adalah pendekatan keamanan. Pasukan keamanan baik dari TNI maupun kepolisan terus menerus dikirimkan ke Papua sebagai respon atas aksi demonstrasi rakyat Papua yang sesungguhnya adalah bentuk kekecewaan pada sikap rasis dari warga negara lainnya yang dialami. Ditambah lagi, yang ditangkapi malah orang-orang di Papua. Bukan pelaku utama di Surabaya. Seakan orang-orang di Papua ini adalah pelaku utamanya.
Rasisme dan diskriminasi di Papua, kata Theo sudah terjadi sejak zaman kolonialisme Belanda. Terutama dalam membicarakan masa depan Papua, tidak diberikan kesempatan yang sistematis pada rakyat Papua untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Saat New York Agreement berlangsung, hanya Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia yang bicara, sementara orang Papua tidak dilibatkan. Bahkan orang Papua yang berniat protes ke New York dihentikan dan ditahan di Port Moresby.

“Sehingga itu jelas untuk kita semua, orang Papua tidak diberikan hak untuk bicara seakan-akan mereka tidak punya hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri, tidak punya hak atas tanah mereka sendiri. Inilah yang menurut saya akar persoalan di Papua,” kata Theo.
Sikap superior seperti ini menurutnya berlanjut hingga hari ini. Orang asli Papua yang berusaha untuk menyampaikan pikiran mereka secara damai melalui demonstrasi, malah ditangkapi. Bahkan demonstrasi itu dilarang dan penggeraknya bisa ditangkapi sebelum melakukan demonstrasi.
Sikap rasis yang menunjukan perilaku superior pemerintah Indonesia terhadap Orang Asli Papua (OAP), menurut tokoh masyarakat Papua Benny Giay memang bukan baru terjadi saat ini. Jauh sebelumnya, pada tahun 60an, saat peralihan Papua dari Belanda ke Indonesia, sikap rasis dan diskriminatif itu sudah ada. Bahkan sikap itu diwujudkan dalam sikap negara pada orang asli Papua untuk menimbulkan nasionalisme Indonesia pada orang asli Papua saat itu.
Giay mengibaratkan perlakuan Indonesia ini sebagai nada dasar untuk membangun Papua. Sejarah dan budaya orang asli Papua dimusnahkan terlebih dulu untuk membangun opini bahwa bangsa Papua tidak punya sejarah, primitif, tinggal di atas pohon, sehingga harus diturunkan agar sejajar dengan suku-suku lain di Indonesia. Kemudian setelahnya ndonesia bisa membangun nasionalisme Indonesia di Papua.
“Sehingga sikap rasis menjadi nada dasar pembangunan Indonesia di Papua. Waktu itu sangat terkenal sekali istilah “mengangkat orang Irian Barat menjadi sejajar dengan suku-suku lainnya di Indonesia”, lanjut Giay.
Fakta sejarah ini menurut Giay membuktikan bahwa rasisme dan diskriminasi yang terjadi pada tahun 2019 lalu bisa berulang kembali di masa mendatang.
Protes anti rasis yang terjadi pada Agustus dan September 2019 menurut Theo bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Protes besar-besaran tersebut merupakan akumulasi dari kekecewaan dan kemarahan rakyat Papua yang terus menerus menerima perlakuan diskriminasi dan rasis dari negara dan warga negara lainnya. Buku yang ditulisnya ini, juga untuk mengingatkan publik bahwa selama beberapa tahun belakangan ini, kita mengalami pengabaian hukum.
“Penegak hukum tidak menjalankan hukum yang ada. Sehingga kita lihat orang-orang ditangkap tanpa ada investigasi. Kita lihat ada berita acara penyelidikan yang direkayasa atau dipaksakan. Dalam persidangan di Jayapura, Nabire, Timika, Fakfak dan Balikpapan selalu muncul saksi-saksi yang tidak beres, tidak ada alat bukti hingga pemindahan tersangka dari Jayapura ke Balikpapan yang melanggar hukum,” jelas Theo.
Semua persidangan ini menurutnya tidak pernah bisa menunjukan apa yang menjadi dasar vonis atas tuduhan makar yang dijatuhkan kepada mereka yang ditangkap di Jakarta dan beberapa kota lainnya di Tanah Papua setelah protes anti rasis terjadi.
“Penegak hukum seharusnya belajar dari kemunduran hukum di Papua yang terjadi selama satu dekade ini,” tutup Theo. (*)