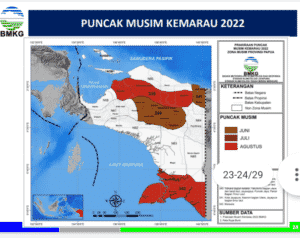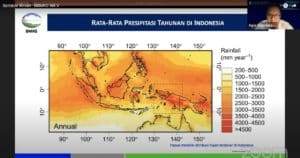Papua No. 1 News Portal | Jubi
Kapal-kapal itu berjejeran. Pertama tampak satu buah. Semakin perahu motor kami ke lautan dua hingga tujuh kapal terlihat. Itu adalah kapal pengangkut produksi milik BP Tangguh LNG.
Kapal dan hutan mangrove merupakan pemandangan yang dijumpai saat perahu bertolak lebih jauh dan menepi di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
Perjalanan ke Babo ditempuh sekira satu jam dengan kapal motor dari Pelabuhan Kota Bintuni. Kami mulai sekitar pukul 09.30 hingga tiba pukul 11.20 waktu Papua.
Di pelabuhan, motor ojek berbaris. Orang-orang lalu-lalang. Tak berapa lama bus pengangkut karyawan BP merapat ke dermaga.
Saya menuju salah satu rumah warga di Kampung Nuse, Distrik Babo. Tak butuh istirahat, merapat ke pusat kerajinan masyarakat binaan lembaga nirlaba–Panah Papua, dan Econusa.
Sekadar diketahui, Bintuni merupakan salah satu daerah dengan hutan mangrovenya. Mangrove Teluk Bintuni terbaik di dunia setelah Raja Ampat. Luas hutan bakaunya sekitar 200 hektare, dan merupakan 10 persen dari luas hutan mangrove di Indonesia.
Hutan mangrove seluas itu menjadikan Kabupaten Teluk Bintuni dapat mengembangkan komoditas perikanan, seperti udang dan kepiting.
Ekowisata
Selain hutan mangrove, Bintuni memiliki hutan gambut terbesar di Papua Barat. Pada 1980, hutan mangrove diusulkan WWF untuk masuk dalam cagar alam. Lalu ditindaklanjuti oleh Konservasi Internaional (CI).
Untuk pengembangan cagar alam, daerah ini masuk dalam kawasan strategis nasional, setelah Raja Ampat, sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
Salah satu program pemerintah daerah setempat adalah peningkatan pembangunan berbasis konservasi. Mangrove dinilai penting bagi perdagangan karbon.
Masyarakat juga didorong untuk berinvestasi, mengingat Bintuni termasuk gas alam cair terbesar, empat kali lebih besar dari Freeport, serta keanekaragaman hayati di lautnya.
Kurangnya promosi menjadi kabupaten dengan luas 20.840,83 kilo dan baru 17 tahun ini, hanya dikenal sebatas BP Tangguh.
Sedikitnya 1,4 hektare hutan bakaunya didorong menjadi kawasan ekowisata.
Ada tiga kawasan di mangrove–transisi, penyangga, dan zona inti. Masyarakat tidak boleh beraktivitas di zona inti. Begitu pun penyangga, yang hanya untuk penelitian, serta kawasan transisi untuk melihat pengembangan ekowisata.
Kampung Masina didorong untuk menjadi kawasan ekowisata mangrove. Tahun ini dibangun spot-spotnya. Tahun 2014 pernah dibangun Tahiti Park, tapi karena urbanisasi dan aktivitas ekonomi meningkat, lahan itu tidak bertahan. Dinas Perikanan bahkan membangun tempat pendaratan ikan di kawasan tersebut.
Tapi kini Masina menjadi kampung ekowisata mangrove berbasis adat. Ekowisata yang cukup besar nanti di Wamesa, Kuri.
Ancaman bagi masyarakat
Laut dan hutan bakau menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat Distrik Babo. Saban hari masyarakat menangkap ikan, udang, dan kepiting atau karaka.
Cara menangkapnya masih tradisional. Menggunakan perangkat, keramba, dan cara tradisional lainnya.
Rutinitas ini dilakukan turun-temurun sejak nenek moyang orang Irarutu di Babo ada.
Namun, kondisi sekarang berbeda. Beberapa tahun belakangan, nelayan dari luar Bintuni merambah kawasan Babo.
Disebut-sebut mereka datang, dari arah barat. Menangkap ikan dengan dalih seizin kelompok-kelompok tertentu.
Dengan peralatan canggih, nelayan luar itu beraksi. Mereka menangkap ikan sampai “trada sisa”.
Informasi ini belum terverifikasi. Tapi ditemukan kapal-kapal masih menancapkan jangkarnya di pelabuhan dan laut sekitar Babo, saat kami menelusuri kawasan hutan bakau dengan perahu jhonson, Selasa, 2 April 2019, sore.
Keberadaan nelayan luar membuat masyarakat lokal tak berdaya. Peralatan canggih, dengan kapal modern, tentu tak bisa disaingi dengan tangkapan tradisional.
Penangkapan untuk nelayan justru terlalu luas, sehingga masyarakat terkena dampaknya.
“Nelayan dari luar lapis dengan alat-alat canggih. Kita rawat lingkungan kalau tidak ada hasilnya bagaimana?” kata seorang warga Distrik Babo.
Usaha oleh-oleh khas Bintuni

Seorang perempuan paruh baya sedang duduk di depan rumahnya, Senin sore, 1 April 2019, di Kampung Argosigenerai, Distrik Bintuni. Namanya Mama Ida Padwa.
Mengenakan kaos merah muda, perempuan beranak empat ini, menerima saya dengan senyuman.
Lalu mempersilakan saya dan beberapa kawan jurnalis, untuk melihat olahannya.
Tampak kemasan keripik dan abon udang di atas meja. Sedangkan yang lainnya masih di penggorengan.
Ini merupakan oleh-oleh khas Bintuni. Siapa pun bisa membawa pulang karya upaya mereka.
Mama Padwa tak sendiri mengolah abon tersebut. Dia dibantu anggota kelompok lainnya. Sekira lima orang banyaknya.
“Kadang-kadang dibantu anak-anak sekolah,” ujar perempuan, yang rumahnya tepat di depan TK Yayasan Pendidikan Kristen Ebenhaezer itu.
Mama Ida bercerita usaha olahannya baru dua tahun. Praktis setelah pelatihan kelompok mama-mama Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2017.
“Modal sendiri, coba Rp 1 juta. Karena (hanya) kepiting sama udang,” katanya.
Meski baru seumur jagung, makanan olahan Mama Ida kerap dipesan ibu-ibu Bhayangkari dan Bank Indonesia. Juga terlibat dalam pameran-pameran.
Seorang kawan bahkan meneteskan air liur, ketika kawan lainnya mengetes abon dan keripik-keripik itu.
“Bawa sudah,” kata Mama Padwa kepada saya, usai diwawancarai di rumahnya.
Istri Pelayan Gereja Ebenhaezer Bintuni, Pendeta F.H. Mofu, itu berpesan kepada perempuan asli Papua, agar percaya diri dengan melakukan usaha, untuk meningkatkan ekonomi dan keterampilannya.
“Karena ini kitong pu tanah,” katanya.
Tak dinyana atas kegigihannya, Mama Ida menjadi utusan kabupaten untuk mengikuti berbagai event, di antaranya, pameran nasional di Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (2018), Lombok, Nusa Tenggara Barat (2017), dan Fakfak, Papua Barat (2016).
Perempuan Papua lainnya, Rekiba Fagiawe, 38 tahun, punya anak tiga. Dia menangkap dan mengolah kepiting untuk kebutuhan rumah tangga. Selain itu juga dia melakukan aktivitas tersebut untuk menyekolahkan anaknya.
“Sehari dapat (kepiting) tergantung keramba. Kalau bulan gelap isi full,” kata Fagiawe.
Bachtiar Rumatumia, Staf Fasilitator Panah Papua, mengatakan ada lima kelompok binaan pihaknya bersama mitra di Bintuni.
Lima kelompok itu adalah Kelompok Maitefa, yang khusus untuk pengembangan ekowisata, Orose untuk pembibitan mangrove, Neromote untuk pendampingan.
Anggota kelompok Neromote disiapkan untuk menjadi semacam pemandu wisata, membuat kerajinan tangan seperti gelang dan mahkota. Sedangkan dua kelompok lainnya adalah Kereru dan Magote.
Bachtiar berpendapat upaya itu sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lokal dan penyelamatan lingkungan, terutama hutan mangrove.
Wilayah pesisir sebagai salah satu kekayaan dari sumber daya alam, yang sangat penting bagi masyarakat dan pembangunan nasional, harus dikelola secara terpadu dan berkelanjutan, serta optimal melestarikan hutan mangrove sebagai aspek pariwisata.
Ekowisata mangrove dianggap menguntungkan masyarakat lokal dengan melibatkan mereka.
“Dengan potensi memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi daerah setempat yang memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian ekosistem mangrove, serta mewujudkan ekonomi berkelanjutan,” katanya.
Kepiting bakau menjadi andalan di Babo sebab tersebar di seluruh pesisirnya. Masyarakat menjual kepiting sekira Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu.
Oleh karena itu, masyarakat lokal diberdayakan untuk mengembangkan usahanya. Di antaranya, mengelola kepiting bakau sebagai mata pencaharian, yang tidak hanya dijual mentah, tetapi juga dalam bentuk olahan.
“Kelompok ini terbentuk pada 25 Oktober 2018 di Kampung Nuse bersama 4 kelompok penangkap kepiting lainnya. Tujuan pembentukan kelompok nelayan ini untuk membangun kebersamaan dalam sebuah komunitas,” kata Bachtiar.
Kepiting olahan masyarakat Babo dijual dalam bentuk abon seharga Rp 50 ribu per bungkus dengan berat bersih lebih dari 500 gram.
Tak hanya itu, Teluk Bintuni bakal dijadikan lokasi Festival Mangrove Nasional dan dikembangkan menjadi kawasan ekowisata.
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Bintuni, Nicolaus Lettungun, mengatakan
Festival Mangrove masuk dalam tahapan kolaborasi.
“Mangrove yang ada di Bintuni bisa terkenal, bukan hanya komunitas lokal, bukan hanya kami, tapi kami juga membutuhkan, pemerintah daerah, provinsi, pusat, karena ini bukan hanya untuk kepentingan masyarakat Bintuni, tapi dunia, Indonsia,” ujarnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari