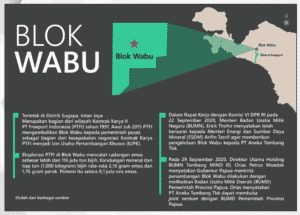Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Dari hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, konflik kekerasan yang terjadi di tanah papua sejak tahun 1965 dan hingga saat ini belum juga menunjukan tanda tanda akan berakhir. Bahkan, ditambah dengan diskriminasi dan marginalisasi terhadap orang asli Papua.
Seiring konflik yang terjadi di Papua, pemerintah kerap menanganinya dengan mengirimkan pasukan non organik yang didatangkan dari luar Papua dengan jumlah mencapai ribuan. Penambahan pasukan yang dilakukan pemerintah itu bukan membuat situasi menjadi kondusif, dan malah menimbulkan konflik baru di berbagai wilayah di Papua, terutama daerah pegunungan tengah Papua.
Pasukan non organik dari luar Papua tidak memahami situasi Papua, membuat mereka acap salah bertindak, menembak warga sipil, bahkan membuat pendeta atau petugas Gereja terbunuh. Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki trauma panjang terhadap kehadiran aparat keamanan pun memilih menghindar, mengungsi demi menghindari nasib sial menjadi korban salah sasaran.
Mereka memilih lari ke hutan lalu bertahan hidup dengan makanan yang ada di hutan. Ribuan warga sipil dari dari konflik seperti Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak, Yahukimo bahkan sampai pergi ke kabupaten tetangga yang dianggap lebih aman, tinggal di pengusian dengan segala keterbatasannya. Warga sipil Kabupaten Pegunungan Bintang bahkan mengungsi hingga ke Papua Nugini. Mereka kehilangan akses pelayanan publik, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan, mengungsi dengan menanggung beban trauma dan rasa ketakutan.
Hilangnya damai di Intan Jaya
Salah seorang ibu yang juga warga pengungsi dari Intan Jaya yang mengungsi ke Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, menceritakan pengalaman ia dan warga lain merasakan damai yang menghilang dari kampung halamannya. “Sebelum ada konflik di Kabupaten Intan Jaya, kami bisa hidup tenang, aman dan damai. Bahkan anak-anak kami bisa bersekolah, masyarakat bisa berkebun. Setelah ada konflik itu, kami seperti menghadapi mimpi buruk,” katanya.
Ibu tersebut mengatakan, lokasi kontak tembak antara pasukan TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) terjadi di Dusun Songandogo, Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Intan Jaya. “TPNPB bermarkas di lokasi dekat Songandogo. Sogandogo adalah tempat beternak babi. Sementara tempat tinggal saya di Kampung Titigi,” katanya.
Ia menuturkan, di Kampung Titigi aparat keamanan membangun sebuah pos penjagaan. Pos penjagaan itu membuat warga tidak bisa bergerak bebas, bahkan warga takut keluar dari rumah mereka.
“Saat aparat TNI/Polri melakukan kontak tembak dengan TPNPB yang berada di Songandogo, kami memilih untuk menghindar. Kami berlindung di Pastoran Titigi, kalau tidak, di dalam gereja Katolik,” katanya.
Baca juga: Menanti konsistensi pemerintah menempuh jalan damai di Papua (1/5)
Ia bercerita, pekerjaan sehari-harinya adalah ibu rumah tangga, sekaligus pelayan di Gereja Katolik Titigi. Di kampung halamannya, ia juga berkebun dan beternak babi.
“Ternak babi milik saya, dan [milik warga yang] lain, juga ikut terkena peluru dari aparat kemanan yang ditujukan kepada TPNPB. Saya hitung-hitung, induk babi betina yang saya punya ada tiga ekor. Anak babi sekitar 30 ekor, sekarang semua mati, habis karena terkena peluru yang ditembak oleh pasukan TNI/Polri. Bahkan satu kandang babi saya juga hancur,” katanya mengenang.
Ia menyebut, tak hanya dirinya yang mengalami kisah pilu tersebut. Mama-mama Papua yang lain juga mengalami persitiwa yang sama, dengan beragam kerugian.
“Saya punya teman-teman juga menjadi korban. Tetangga saya, masyarakat yang lain, juga kehilangan ternak, rumah, kebun, semua menjadi korban oleh aparat kemanan,” katanya.
Namun lebih dari itu, ia merasa setiap Orang Asli Papua di Intan jaya dicurigai aparat kemanan. Di Intan Jaya, sejumlah warga sipil asli Papua yang telah menjadi korban dari kecurigaan itu—terkena tembakan, diculik, dibunuh.
Baca juga: Kisah anak tokoh OPM dan TPNPB, dari menjadi buronan sampai didiskriminasi (2/5)
“Kami mau lari ke mana? Kalau kami tinggal di Titigi, juga dicurigai oleh aparat TNI/Polri, dan bisa terkena peluru nyasar dari TPNPB juga. Kami merasa tidak aman tinggal di tanah kami sendiri, sehingga kami meninggalkan kampung halaman kami,” katanya.
Anak-anaknya pun hidup dalam ketakutan, karena tembakan demi tembakan selalu terdengar di Titigi. “Anak-anak kami sudah tidak bisa bersekolah lagi karena penembakan yang terjadi di intan Jaya. Selama di Intan Jaya, kami bersama masyarakat merasa ketakutan karena ada bunyi penembakan,” katanya.
Dia menuturkan bagaimana konflik bersenjata di Titigi itu membuat warga tak bisa beraktivitas. Warga sipil yang telah mengungsi di gereja pun dicurigai kedua belah pihak yang bertikai, TNI/Polri maupun TPNPB.
“Kami mau pergi ke kebun ka, ke kandang babi, tidak bisa, sebab TNI/Polri dan TPNPB saling berjaga. Kami merasa tidak aman. Kalau kami bergerak, kami bisa saja dicurigai oleh kedua belah pihak,” katanya.
Baca juga: Kisah pilu dalam bayang-bayang kemerdekaan Papua (4/5)
Dia juga kecewa karena saudaranya yang juga seorang dengan gangguan kejiwaan terbunuh dalam konflik bersenjata itu. Ia merasa tak punya pilihan selain merelakan adiknya itu, merasa tak punya harapan untuk melihat para pelaku pembunuhan itu bakal diadili.
“Meski kecewa, dengan besar hati dan buka hati kami sudah menyerahkan adik kami sebagai seorang pahlawan untuk Papua. Dia meninggal dan dibunuh oleh aparat keamanan dengan cara yang biadab. Dengan adanya keterlibatan aparat keamanan yang banyak dan membunuh warga sipil yang tidak berdosa, termasuk adik saya yang memiliki gangguan jiwa, kami merasa takut,” katanya.
Langkah aparat keamanan merespon konflik bersenjata di Intan Jaya kerap kali tak menenangkan warga. Misalnya, pasukan TNI/Polri mendirikan pos pengamanan di salah satu paroki yang dipimpin Pastor Yance Wadogoubi Yogi. Pos itu justru membuat warga sipil yang mengungsi ke sana merasa takut, sehingga membuat mereka justru mengungsi ke tempat yang lebih jauh.
“Kenapa lagi aparat TNI/Polri membangun pos di situ? Di situ tempat masyarakat kami beribadah. Kami merasa tidak aman, jadi kami mengungsi,” kata sumber Jubi yang tidak mau disebutkan namanya itu.
Baca juga: Menyeru dialog dan demiliterisasi, merawat asa damai untuk Papua (5/5)
Sumber itu bercerita, awalnya jemaat di Titigi itu berencana membangun Pastoran, namun rencana itu terhenti karena konflik bersenjata di sana. Apalagi, kini semakin banyak jemaat di Titigi yang memilih mengungsi ke tempat lain.
“Yang tersisa hanya Pastor dan beberapa umat saja yang ada di Titigi. Jika kami dari Dusun Songandogo mau datang ke gereja di Kampung Titigi, kami selalu ditanya-tanya oleh aparat keamanan yang ada di situ. ‘Kalian dari mana mau ke mana?’ Mereka hampir setiap Minggu tanya kami. [Bagi] kami yang sudah biasa dilihat oleh mereka, itu aman. Tetapi, kalau wajah baru yang datang di Titigi, itu dalam ancaman bahaya,” katanya.
Ia juga bersedih lantaran rumah hancur terkena kena tembakan aparat keamanan maupun TPNPB. “TNI yang bertugas di kampung-kampung itu biasa meminta buah-buahan. Alpukat, markisa, dan saya biasa kasih ke mereka. Tetapi perlakuan mereka terhadap kami, rumah kami ditembak, itu membuat kami sakit hati,” katanya.
Mencari aman di Nabire
Banyak di antara warga Intan Jaya mengungsi ke Nabire, ibu kota Kabupaten Nabire yang merupakan “gerbang” menuju sejumlah kabupaten di Wilayah Adat Meepago yang tengah memanas karena konflik bersenjata di sana. Para pengungsi yang ditemui Jubi di Nabire menuturkan kehidupan mereka yang penuh keterbatasan, lantaran jauh dari kampung halamannya.
Mengungsi ke Nabire pun tak sepenuhnya memberi rasa aman bagi mereka, karena mereka merasa aktivitasnya selalu dipantau aparat intelijen. “Ruang gerakan kami di kota ini juga agak susah. Meskipun kami berada di pengungsian, banyak intel yang menyamar menjadi tukang ojek, atau penjual sayur, sering memata-matai kami,” katanya.
Situasi itu membuat para warga yang mengungsi merasa mengalami kekerasan berganda. Mereka warga yang tidak terlibat konflik bersenjata, tidak tahu apa-apa, namun setelah mengungsi pun selalu dicurigai.
“Desember ini, kami sudah tinggal satu tahun di Nabire Papua. Kehidupan di Nabire itu berbeda jauh dengan saat kami berada di kampung dulu. Tantangan hidup di kota ini jauh lebih berat daripada di kampung,” katanya.
Baca juga: Presiden Jokowi diminta konsisten mewujudkan statementnya pada 30 September 2019
Jauh dari kebunnya, para pengungsi dipaksa bertahan hidup di kota, tanpa memiliki sumber penghidupan. “Di kota ini, kami mau pergi ibadah Mingguan juga harus mengeluarkan transportasi, gerejanya juga jauh jaraknya, sehingga membutuhkan biaya hidup yang besar. Berbeda dengan di kampung. Di tempat pengungsi, di Nabire, [jika terus] berada di tempat pengungsian itu, kami bosan. [Kami] mau pulang ke kampung halaman, tapi tidak aman. Dengan keadaan terpaksa, kami tinggal di sini,” katanya.
Berada di Nabire juga tidak membuat para pengungsi terlepas dari beban memikirkan nasib saudara-saudara mereka yang masih berada di Intan Jaya, ataupu mengungsi ke berbagai kabupaten tetangga lainnya. Konflik bersenjata di Intan Jaya benar-benar mencerai-beraikan warga sipil yang mengungsi secara terpisah-pisah, di Nabire, di Timika, atau masuk ke hutan.
“Kami merayakan Natal 2021 apa adanya, dengan keluarga kami yang ada di Nabire. Kami juga terpikir dengan kondisi pengungsi yang ada bersama dengan kami, dan [saudara-saudara kami yang mengungsi] di daerah lain. Perayaan Natal di pengungsian tidak sama seperti kami merayakan Pesta Natal di kampung halaman kami sendiri. Saat kami berada di kampung, kami punya kebun [yang] kami kerjakan, bisa pergi ke gereja mengikuti ibadah dengan tenang dan aman,” kata seorang ibu yang berlatarbelakang petani.
Kebanyakan warga sipil Intan Jaya yang mengungsi itu menggantungkan penghidupannya dari bertani dan berkebun. Di Nabire, mereka tidak bisa begitu saja membuka lahan dan berkebun, karena bisa berselisih paham dengan warga setempat. Masalahnya, kebanyakan dari mereka tidak memiliki keahlian selain berkebun.
Baca juga: Polisi ubah satuan tugas Nemangkawi menjadi operasi Damai Cartenz, ini penjelasannya
“Kami mau bertani juga agak susah, sebab kami tidak punya tanah di Nabire. Syukur-syukur kalau ada keluarga yang memunyai tanah di Nabire. Mereka bisa mengelola tanah untuk mendapatkan makan, dan sebagian berjualan di pasar. Kalau di kampung, sebagian panenan hasil kebun kami jual untuk beli kebutuhan dapur [seperti] beras, garam, minyak [goreng], atau gula, teh, kopi. Tetapi di sini, kepada siapa kami mau bergantung hidup?”
Para pengungsi Intan Jaya di Nabire tinggal terpencar-pencar, ada dalam kelompok kecil yang terserak di berbagai tempat, sebagian tinggal menumpang sanak saudaranya. Kondisi itu membuat mereka kesulitan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.
Pengungsi berharap Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan Pemerintah Kabupaten Nabire bisa mencarikan solusi atas persoalan itu. “Tidak ada juga sekolah sekolah alaternatif yang bisa membantu anak-anak kami untuk bersekolah,” kata salah satu pengungsi.
Baca juga: Demi perdamaian Papua, Dewan Gereja Papua minta Jokowi penuhi janji
Karena saling berpencar, kondisi kesehatan para pengungsi tidak terpantau, bahkan tidak ada yang bisa mendata berapa jumlah warga pengungsi yang sakit atau meninggal. “Kami belum bisa mendata mereka yang sudah meninggal dunia, karena kami tinggal berpencar, tidak satu tempat. Rata-rata pengungsi meninggal dunia karena sakit malaria, sebab di Nabire itu berbeda dengan dengan Intan Jaya sana. Mereka susah menyesuaikannya, sehingga mereka meniggal dunia,” katanya.
Berbagai kalangan warga sudah berupaya membantu para pengungsi Intan Jaya di Nabire. Bantuan itu biasanya dikumpulkan para mahasiswa, gereja, ataupun organisasi lainnya. Salah satu pengungsi menuturkan, terkadang ada orang datang menawari bantuan, dengan syarat para pengungsi mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka. Permintaan itu selalu ditolak para pengungsi.
“Kemarin ada bantuan dari Paroki Bumi Raya di Wonorejo. Kami sudah salurkan kepada warga pengungsi yang ada di Satuan Pemukiman C. Kalau ada orang yang datang kepada kami untuk meminta KTP [sebagai syarat] menyerahkan bantuan, kami tidak akan terima, kami tidak akan memberikan KTP kami,” katanya.
Anak-anak di Pengungsian
Selain perempuan dan orang lanjut usia, kebanyakan pengungsi Intan Jaya di Nabire adalah anak-anak, termasuk anak usia sekolah. Para pengungsi Intan Jaya sangat berharap anak-anak mereka bisa bersekolah di tempat mereka mengungsi, namun rasa takut selalu mengikuti mereka.
“Kami mau agar anak-anak kami bisa bersekolah di Nabire, Jayapura, Timika. Tapi kami khawatir, siapa yang akan memerhatikan mereka di sana? Kami khawatir anak-anak kami dapat ancaman teror, sehingga membuat kami tidak aman dan berada dalam ketakutan. [Kalau] kami memasukkan anak-anak kami bersekolah di kota ini, kami juga takut mereka mendapatkan diskriminasi [karena mereka] anak-anak pengungsian. Kami juga takut anak-anak kami akan dipantau oleh intelijen,” katanya.
Itu sebabnya hasrat terbesar para pengungsi adalah kembali ke kampung halamannya. Mereka lelah dengan situasi mereka sebagai pengungsi, dan ingin segera menjalani aktivitas normal, sebagaimana orang yang tidak hidup di daerah konflik. Mereka juga ingin anak-anak mereka tumbuh dengan normal sebagaimana anak yang tidak berasal dari daerah konflik.
Baca juga: Negara harus upayakan solusi damai untuk akhiri konflik di Papua
Akan tetapi, selama pasukan TNI/Polri belum ditarik dari Intan Jaya, mereka juga tak berani kembali ke kampungnya. Tanpa itu, para pengungsi takut bakal menjadi korban kekerasan yang terus terjadi di Intan Jaya.
“Anak-anak kami tidak cocok bersekolah di Nabire ataupun di tempat pengungsian lain. Supaya anak-anak ini bisa sehat dan bisa mendapatkan pendidikan yang baik, pemerintah bisa memulangkan anak-anak dan masyarakat ke Intan Jaya.
Saat pengungsi Intan Jaya masih terkonsentrasi di Jayanti, sejumlah pengungsi berinisiatif untuk menghadirkan sekolah alternatif bagi anak-anak pengungsi Intan Jaya di Nabire. Akan tetapi, upaya itu terkendala kondisi para pengungsi yang berpencaran.
“Kami berencana mendirikan sekolah alternatif untuk membina anak-anak dari pengungsian. Tetapi tidak sempat, karena pengungsi yang semula tinggal di Jayanti sudah berpencar ke Wadio, Kali Pepaya, SP C, dan dibeberapa tempat lainnya. Agak susah kami mengontrol mereka,” kata salah satu pengungsi.
Baca juga: PNG selidiki korban konflik bersenjata di Pegunungan Bintang yang menyeberang ke Tumolbil
Salah satu Mama dari Intan Jaya menuturukan ia berupaya membimbing anak-anaknya untuk rajin berdoa kepada Tuhan, tidak nakal, dan belajar menghargai orang lain. Ia juga berupaya menghapus trauma sang anak, agar tak berkembang menjadi dendam. “Saya menasehati agar anak saya tidak lagi nakal atau membunuh orang sembarang, sebab itu melanggar perintah Tuhan, sebagaimana yang tercatat dalam Alkitab,” tuturnya.
Ia mengaku sedih dengan konflik bersenjata di Intan Jaya yang tak kunjung berakhir. Konflik ini terjadi di terjadi di depan anak-anak. Mereka hidup di bawah tekanan militer, intimidasi, teror. Bahkan, saat berada di Intan Jaya, rumah masyarakat ditembak, sementara masyarakat berada dalam honai bersama dengan anak-anak mereka,”katanya.
Ia cemas lantaran di pengungsian anak-anak tidak belajar, tidak mendapatkan pelayanan dan pendidikan agama yang memadai. Sehari-hari anak-anak pengungsi hanya bermain-main, terkadang mereka ikut bapak atau mama pergi ke kebun untuk bikin kebun.
“Saat kami masak bersama, duduk berkumpul bersama, kami selalu menyampaikan pesan-pesan poisitif kepada anak-anak. ‘Kalian harus rajin ibadah di gereja, sekolah minggu agar supaya kalian bisa bertumbuh dalam iman’,” katanya.
Baca juga: Ingin kembalikan pengungsi ke Nduga, pemerintah pusat diminta tarik pasukan non-organik
Para Mama yang menjadi korban konflik bersenjata itu tidak mau anak-anak mereka mewarisi dendam. Mereka juga tidak mau anak-anak mereka terbelenggu dalam meraih cita-citanya, entah itu menjadi Pegawai Negeri Sipil, Camat, atau cita-cita lainnya.
“Kami tidak mengajarkan kebencian kepada anak-anak di pengungsi. Kami biarkan mereka bermain dengan teman teman mereka, sebab selain ke kebun, itu hiburan bagi mereka di tempat pengungsi. Kami hanya menanti, kapan daerah kami damai, dan anak-anak kami mereka bisa kembali melakukan aktivitas sekolah mereka. Kami harus pulang, tetapi jalan satu satunya kami berdoa untuk mengakhiri konflik, [agar] tidak ada lagi bunyi tembakan yang membuat kami ketakutan dan anak-anak kehilangan masa depan,” kata salah satu Mama.
Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar mengatakan pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap keberadaan pengungsi, khususnya anak-anak yang terdampak konflik bersenjata di Papua. Jika trauma anak-anak itu tidak tertangani dengan baik, mereka akan tumbuh dengan luka yang mendalam, yang bisa membawa mereka bergabung dalam gerakan perlawanan bersenjata di Papua.
“Karena, mereka melihat pemerintah tidak menangani mereka selama berada di lokasi pengungsian, di tengah hutan. Cepat atau lambat, itu akan terjadi, sehingga [trauma para anak terdampak konflik] itu harus ditangani,” katanya.
Baca juga: JDP: Gagasan dialog damai mesti jadi gerakan bersama
Siregar mengkritik pemerintah yang sibuk membangun infrastruktur di Papua, namun mengabaikan pentingnya upaya pemulihan para korban konflik Papua. “Orang Papua sudah berada dalam trauma yang berkepanjangan. Jika dibiarkan terus, mereka akan mengalami dan menjadi korban bertubi-tubi. Saat mereka [kemudian] berontak lagi, Negara Indonesia mau salahkan siapa?” tanya Siregar.
Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas mengatakan profil para aktor kekerasan di Papua hari ini berkaitan langsung dengan berbagai praktik kekerasan dan pelanggaran HAM aparat keamanan pada era 1970 – 1990-an. Ia menyebut tokoh gerakan Papua merdeka seperti Benny Wenda dan tokoh TPNPB Egianus Kogoya adalah korban kekerasan dan pelanggaran HAM pada masa lalu itu.
Cahya menilai trauma mereka menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM itulah yang membuat mereka melakukan gerakan memperjuangkan kemerdekaan Papua. “Sewaktu kecil keluarga mereka banyak yang terbunuh akibat operasi militer di pegunungan tengah pada tahun 1977 – 1978. Yang lain juga demikian. Pemimpin politik saat ini, mereka pada masa kecilnya menjadi korban dari suatu operasi militer pendekatan keamanan,” kata Cahyo.
Entah mengapa, pemerintah belum juga menunjukkan upaya seriusnya untuk menangani nasib warga sipil Papua yang mengungsi karena konflik bersenjata. Yang terjadi justru konflik bersenjata itu semakin meluas, terjadi di berbagai wilayah yang dahulu damai dan jauh dari bunyi tembakan. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G