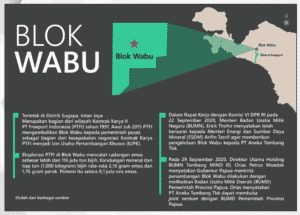Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Aktivis perempan Papua, Sofia “Poppy Maipauw mengatakan perempuan Papua terus mengalami kekerasan sejak tahun 1961 hingga 2021. Siklus kekerasan yang terus berulang itu disebabkan berbagai kebijakan pemerintah pusat yang justru menimbulkan ketidakpercayaan orang asli Papua, dan stigmatisasi terhadap orang asli Papua.
Hal itu dinyatakan Maipauw selaku pembicara dalam diskusi daring Perempuan Papua Bicara yang dilenggarakan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia pada Rabu (30/6/2021).“Perempuan Papua berbicara tentang keselamatan manusia Papua dan Tanah Papua, [tapi] justru dipandang sebagai separatis. Jika cara pandang Jakarta demikian, persoalan tidak pernah terselesaikan,” kata Maipauw.
Ia mengingatkan, sejarah panjang kekerasan di Tanah Papua membuat 100 tokoh Papua menemui Presiden BJ Habibie pada 1999, dan menyatakan meminta kemerdekaan Papua. Permintaan 100 tokoh Papua itu kemudian dijawab pemerintah pusat dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua).
Baca juga: Pemberdayaan perempuan di kampung harus terus ditingkatkan
Akan tetapi, pasca berlakunya UU Otsus Papua, orang Papua tetap kerap mengalami kekerasan dan dicurugai. Otsus Papua telah berlangsung selama 20 tahun, namun konflik politik antara Jakarta dan Papua kerap berubah menjadi kekerasan yang berimbas kepada perempuan Papua dan anak.
“Otsus diberikan untuk menyelesaikan persoalan Papua dari empat aspek kehidupan, pendidikan kesehatan, ekonomi, infrastruktur. Termasuk juga keterlibatan perempuan Papua dalam politik. Selama 20 tahun berapa jumlah perempuan papua yang berhasil di bidang usaha? Tentu belum banyak. Hal itu karena tidak adanya peran yang diberikan kepada perempuan Papua untuk berkarya. Selama 20 tahun, Otsus Papua tidak berdampak kepada perempuan Papua,” katanya.
Ia menyatakan perempuan Papua harus diberi kesempatan menjadi agen perdamaian di Papua. Akan tetapi, dalam praktiknya, perempuan Papua justru terus menjadi korban kekerasan di Papua. “Kami minta kepada pemerintah pusat, stop datangkan militer ke Tanah Papua. Karena imbas dari penempatan aparat secara berlebihan, perempuan Papua selalu menjadi korban dalam berbagai operasi di Tanah Papua,” katanya.
Maipauw menyatakan awalnya banyak aktivis perempuan Papua meyakini Otsus Papua bisa menjadi jalan keluar atas siklus kekerasan terhadap perempuan Papua. “Perempuan Papua juga beranggapan bahwa Otsus Papua akan mengantarkan perempuan Papua keluar dari kekerasan konflik. Namun hasilnya juga tidak seperti yang kami bayangkan. Kami perempuan Papua kehilangan akses dalam aspek politik, ekonomi, bahkan pendidikan. Untuk mendapatkan sesuatu, kami harus berjuang mati-matian. Kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan Papua sangat lemah,”katanya.
Sekertaris Komisi Keadilan dan Keutuhan Ciptaan GKI Tanah Papua Klasis Port Numbay, Pdt Anike Mirino mengatakan berbagai kasus kekerasan masih terjadi di Tanah Papua. Hal itu antara lain terlihat dari konflik bersenjata yang menyebabkan warga sipil di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, dan Puncak mengungsi dari tempat tinggal mereka.
Baca juga: Komnas Perempuan mendesak kebijakan mencegah pelecehan seksual di tempat kerja
Mirino menyebut dalam situasi konflik itu, perempuan selalu menjadi kelompok yang paling terdampak konflik. “Mayoritas pengungsi adalah ibu dan anak-anak yang berada di daerah pengungsian. Mereka meniggalkan kampung halaman, dipaksa keluar dari akar budaya mereka, meninggalkan harta kekayaan mereka. Itu pelanggaran Hak Asasi Manusia besar yang diabaikan negara,” kata Mirino.
Mirino mengatakan para warga sipil dari ketiga kabupaten juga harus mengungsi dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan lebih dari setahun, sehingga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka mengungsi. Para warga sipil yang mengungsi ke kabupaten lain, mengungsi ke Wamena ibu kota Kabupaten Jayawijaya misalnya, juga kehilangan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.
“Itu satu masalah lagi, bagaimana mereka harus bisa menyesuaikan hidup dengan kebiasaan masyarkat setempat di Wamena [misalnya]. Masyarakat yang ada di pengungsian itu harus mendapatkan trauma healing untuk menghilangkan rasa takut yang berkepanjangan, agar anak-anak itu bisa mendapatkan tempat di masyarakat dan bersekolah, karena mereka itu masa depan Papua,” kata Mirino. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G