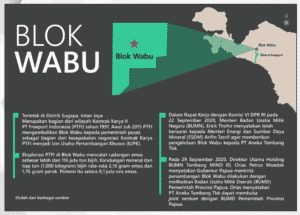Papua No. 1 News Portal | Jubi
Yogyakarta, Jubi – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua atau Ipmapa Surabaya menuntut digelarnya referendum bagi bangsa West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Referendum itu dinilai akan menjadi solusi demokratis untuk mengakhiri praktik rasisme, diskriminasi, persekusi, dan intimidasi yang selama berpuluh tahun dialami orang Papua.
Tuntutan itu disampaikan Ipmapa Papua melalui siaran pers yang diterima Jubi pada Minggu (25/8/2019). Dalam siaran pers yang ditandatangani pengurus Ipmapa Papua Surabaya dan 23 koordinator wilayah dan paguyuban mahasiswa Papua dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur itu, Ipmapa Papua menyatakan rasisme aparatur negara Indonesia telah terjadi sejak Indonesia menguasai Papua pada 1962, dan menjadi sumber penyebab berbagai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus-menerus dialami orang Papua.
“Untuk mengakhiri rasisme-yang adalah anak kandung dari imperialisme yang mengkoloni West Papua-maka segera selenggarakan referendum di Tanah Papua, sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua. Rasisme, sikap dan tindakan merendahkan martabat harga diri rakyat Papua, telah lama dilakukan lewat operasi-operasi militer,” tulis Ipmapa Papua dalam siaran persnya.
Ipmapa Surabaya menyatakan sikap rasisme dengan makian “monyet Papua” datang dari kelompok reaksioner berwatak kolonial. Ipmapa Surabaya menyebut kolonialisme di Papua sudah berlangsung sejak pelaksanaan Perjanjian New York yang ditandatangani Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat pada 15 Agustus 1962.
Atas dasar perjanjian itu, Belanda menyerahkan penguasaan wilayah Papua kepada Indonesia pada 1963. Ipmapa Surabaya menekankan, rasisme terhadap orang Papua bukanlah peristiwa baru sebagaimana terjadi dalam pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu. Rasisme terhadap orang Papua memiliki rekam sejarah yang panjang, melatarbelakangi penindasan, diskriminasi, dan pembungkaman ruang demokrasi terhadap mahasiswa Papua dan rakyat Papua.
Tuntutan digelar referendum bagi Papua itu menjadi bagian dari 14 pernyataan sikap Ipmapa Papua dalam siaran pers tertanggal 24 Agustus 2019 itu. Ipmapa Surabaya juga menyatakan para pelajar dan mahasiswa Papua di Surabaya akan pulang meninggalkan Indonesia jika Papua diberi Hak Penentuan Nasib Sendiri.
Ipmapa Surabaya juga menyatakan akan menolak kunjungan Pemerintah Jawa Timur beserta aparat keamanan seperti TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja, karena mereka dinilai menjadi aktor dibalik pembungkaman demokrasi dan pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. Ipmapa Surabaya bahkan menolak kunjungan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat, serta menolak semua bantuan berbau politis dari pihak manapun.
Ipmapa Surabaya meminta Pemerintah Indonesia menghentikan agenda pencitraan yang melibatkan mahasiswa Papua di seluruh Indonesia, dan menolak anggapan bahwa Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) merupakan representasi pelajar dan mahasiswa Papua di Jawa Timur.
Selain mengecam rasisme terhadap orang Papua, Ipmapa Surabaya menuntut Pemerintah Indonesia menarik militer organik dan non-organik dari seluruh Tanah Papua. Ipmapa Surabaya meminta Pemerintah Indonesia segera membuka akses peliputan di Papua bagi seluruh jurnalis lokal, nasional, maupun internasional, dan menuntut pemerintah segera mengakhiri pembatasan akses internet di Papua. Mereka juga menutut semua perusahaan nasional dan internasional di Tanah Papua ditutup.
Ipmapa Surabaya menyeru agar Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan para pelajar dan mahasiswa Papua di seluruh wilayah Indonesia. Komisi HAM PBB dminta segera meninjau berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, dan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Papua di West Papua. Ipmapa Papua juga menyeru agar jaringan Gereja-gereja bersama jaringan advokasi HAM di tingkat nasional dan internasional segera memantau kondisi HAM di Papua.
Secara terpisah Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati saat dihubungi di Jakarta pada Minggu (25/8/2019) menyebutkan bermuaranya persoalan rasisme terhadap orang Papua kepada tuntutan referendum terjadi karena praktik diskriminasi dan rasisme terhadap orang Papua terjadi secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama. “Sejak 2017, sudah terjadi kecenderungan untuk membenturkan aspirasi politik para mahasiswa Papua dengan organisasi kemasyarakatan,” kata Afinawati.
YLBHI mencatat pada 2018-2019 sedikitnya terdapat 33 peristiwa pelanggaran HAM yang dialami mahasiswa Papua. “Peristiwa itu berupa intimidasi, tindakan rasis, penggerebekan asrama, penyerangan asrama, pembubaran diskusi, pembubaran aksi, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan sewenang-wenang, penganiayaan, serta pembiaran pelanggaran hukum dan HAM oleh aparat penegak hukum. Dari 33 peristiwa itu, sembilan terjadi di Surabaya,” kata Asfinawati.
Asfinawati menegaskan tuntutan referendum dari berbagai pihak, termasuk Ipmapa Surabaya, harus didudukkan dalam konteks orang Papua dan mahasiswa Papua selama bertahun-tahun mengalami ketidak-adilan, rasisme, dan diskriminasi. “Itu menjelaskan mengapa tuntutan referendum muncul. Di dalam hukum, tuntutan Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri adalah ekspresi politik yang sah, bagian dari hak dasar manusia. Sepanjang tuntutan Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri itu disampaikan secara damai, Negara dan aparaturnya wajib melindungi penyampaian ekspresi politik itu. Negara dan aparatur Negar tidak boleh merepresi ekspresi politik itu,” kata Asfinawati.
Asfinawati menyebutkan, cara Pemerintah Indonesia menangani persekusi dan rasisme di Surabaya buruk, dan semakin memperburuk situasi. “Hal pertama yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah adalah menyangkal telah terjadi persekusi dan rasisme. Kedua, setelah fakta persekusi dan rasisme itu tidak terbantahkan, Pemerintah Indonesia justru meminta orang Papua memaafkan. Ketiga, Pemerintah Indonesia membangun kerangka berfikir bahwa gelombang unjukrasa dan amuk massa di Papua terjadi karena hoax. Hal itu semakin menyakiti orang Papua, membuat orang Papua semakin merasa praktik diskriminasi itu nyata,” ujar Asfinawati.
Asfinawati menyebut, resistensi aparatur Negara untuk mengakui adanya persekusi dan rasisme di Surabaya menyebabkan aparat penegak hukum lamban dalam menjalankan pemidanaan terhadap para pelaku. “Hingga kini, belum ada pelaku persekusi dan rasisme yang dijadikan tersangka. Yang terjadi justru Pemerintah Indonesia menutup akses internet di Papua. Orang Papua adalah korban dalam kasus ini, namun justru orang Papua yang mendapatkan pembatasan hak. Di dalam hukum, seharusnya pelakulah yang mendapatkan pembatasan hak. Cara aparatur Negara menangani kasus ini semakin menegaskan adanya diskriminasi hukum terhadap orang Papua,” kata Asfinawati. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G