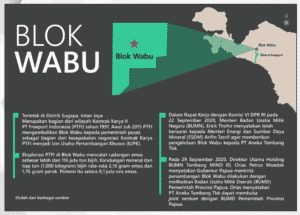Papua No. 1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Dorlince Iyowou, seorang mahasiswi Papua di Asrama Kamasan Surabaya, bersama belasan mahasiswa lainnya dipaksa turun dari lantai dua asrama dalam keadaan merayap dan jongkok.
“Kami hanyalah ‘monyet-monyet’ yang dikeluarkan paksa dari Honai dengan 5 tembakan gas air mata dari luar dan 14 gas air mata di dalam asrama, memaksa kami turun daru lantai dua asrama dalam keadaan merayap, jongkok, percepat sambil tembakan-tembakan (gas air mata) itu dalam jarak yang dekat,” ungkap Iyowou kepada Jubi, Minggu (18/8/2019).
Sepotong kesaksian Dorlince Iyowou itu merangkum peristiwa penangkapan 43 mahasiswa dari asrama mahasiswa Papua Kamasan Sabtu sore (17/8/2019). Mereka ditangkap tanpa alasan yang jelas, lalu dibebaskan tengah malamnya setelah rangkaian interogasi polisi tidak menemukan bukti bahwa mahasiswa Papua yang membuang bendera merah putih di depan asrama ke selokan.
“Saya sehat. Tapi lima orang dapat pukul dan satu kena gas air mata, kakinya picah (luka berat),” kata Dorlince.
Secara terpisah, Jubi meminta pendapat beberapa aktivis dan dosen dari Jawa Timur terkait peristiwa yang melukai banyak hati warga Papua ini.
Koordinator Nasional Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) yang berbasis di Jawa Timur, Roy Murtadho, saat diminta tanggapannya oleh Jubi Minggu, (18/8/2019), mengutuk peristiwa itu.
“Menurut saya ini tindakan brutal dan rasis yang justru diprovokasi oleh aparatur negara yakni TNI,” katanya dari Jakarta. Dia menduga ada skenario lain dari kejadian kekerasan ini.
“Dugaan saya sementara kejadian di Surabaya, Malang dan sekarang di Semarang adalah bagian dari skenario untuk mendiskreditkan gerakan Papua untuk menentukan nasibnya sendiri di mata publik Indonesia,” ungkap Gus Roy, panggilang akrabnya.
Dia mengakui pokok persoalannya memang adanya prasangka dan kebencian rasial kepada warga Papua. “Apalagi pemerintah selalu mereproduksi hoax tentang sejarah Papua, maupun perjuangan kemerdekaan Papua,” lanjutnya.
Senada dengan itu, aktivis kawakan dan dosen tidak tetap Universitas Airlangga, Dede Oetomo juga mengkritisi aparat keamanan dan organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan intimidasi dan persekusi terhadap orang Papua yang berada di luar Papua. Menurut Dede, sikap reaksioner itu cerminan ketakutan rezim dan aparat keamanan terhadap kebangkitan nasionalisme Papua.
“Seingat saya ini fenomena itu [muncul] beberapa tahun belakangan, karena ada kesadaran nasionalis baru di kalangan orang muda Papua. Lalu itu direpresi oleh pemerintah, termasuk menggunakan preman. Yang diincar asrama mahasiswa Papua. Karena rezim merasa sangat terancam dengan kebangkitan kesadaran nasional Papua, dan melakukan apa saja untuk merepresinya,” papar Dede.
Dede mengakui adanya potensi rasisme warga Surabaya dan Jawa Timur terhadap mahasiswa Papua yang ada di sana. “Iya, [potensi rasisme itu ada,] karena propaganda rezim tentang Papua juga masif dan merasuk ke warga kebanyakan. [Terutama di kalangan warga] yang tidak tahu sejarah [Papua],” lanjutnya.
Kecewa pada penegak hukum
Herlambang P Wiratraman, Ketua Pusat Studi Hukum HAM, Fakultas Hukum Universitas Airlangga juga angkat bicara menyikapi peristiwa Kamasan Surabaya. “Saya prihatin sekaligus kecewa aparat penegak hukum dan pemerintah yang tak mampu mencegah kekerasan dan memberi rasa aman, khususnya bagi warga Papua yang ada di Surabaya dan Malang,” katanya.
Dia juga menyebutkan aparat kepolisian terlalu berlebihan menggunakan senjata. “Bila ada pelanggaran hukum, proses sebagaimana mestinya, namun begitu juga terhadap mereka yang melakukan kekerasan,” ujarnya.
Dia menegaskan setiap warga negara berhak atas ekspresi, dan ekspresi tersebut dijamin UUD 1945. “Tidak boleh siapapun warga lakukan main hakim sendiri, menghukum atau bahkan gunakan kekerasan. Atas tindakan tersebut, penegak hukum tidak boleh membiarkan atau bersikap permisif terhadap kekerasan,” katanya lagi.
Herlambang menekankan bahkan untuk tuntutan dan ekspresi pendapat terkait self determination atau hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak asasi manusia yang diatur dalam pembukaan UUD 1945, dan Konvenan Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia.
“Bila perlakuan terhadap warga Papua terus menerus dengan pendekatan kekerasan, eksploitasi sumberdaya alam, dan penyingkiran hak-hak, maka itu semua bentuk pembodohan dan pemiskinan. Itu justru mengingkari cita-cita bangsa Indonesia sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945,” kata dia.
Herlambang menambahkan potret kekerasan ini adalah cerminan tiadanya jaminan kebebasan ekspresi dan kebebasan akademik bagi mereka yang mengkaji dan berfikir kritis atas realitas ketidakadilan di Papua.”Perlakuan kekerasan karena stigma di tengah masyarakat, dan itu seperti merawat konflik agar tetap terjadi. Kawan-kawan mahasiswa Papua yang selalu dikorbankan,” katanya lagi.
Berharap kepada NU
Gus Roy menaruh harapan terbesarnya kepada Nahdatul Ulama (NU) untuk mereduksi sentimen rasial dan sikap anti Papua yang kini menguat di Jatim. Roy mengingatkan sentimen anti Papua mudah dijadikan alat propaganda fasisme oleh tentara, dengan memberi insentif finansial maupun sosial pada ormas fasis seperti FPI dan Pemuda Pancasila.
“Saya menaruh harapan besar kepada NU, untuk membuktikan komitmennya pada prinsip demokrasi dan kemanusiaan, dengan minimal mengeluarkan maklumat mengutuk dan mengharamkan tindakan rasis seperti kerap dilontarkan tentara, ormas fasis seperti PP atau FPI, karena itu mengkhianati spirit egalitarianisme dalam Islam,” ungkap aktivis yang kerap bersuara lantang di internal NU ini.
Roy meyakini NU akan bisa mengembalikan karakter asli masyarakat Jawa Timur yang terbuka dan egalitarian. “Yang kita kenal Jatim itu masyarakatnya lebih terbuka dibanding misalnya di Jogja. (Tapi jadi bisa makin rasis) karena kelompok nasionalis tengah atau moderat seperti NU belum berani mengambil langkah lebih maju seperti apa yg dulu dilakukan Gus Dur,” tegasnya.(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G