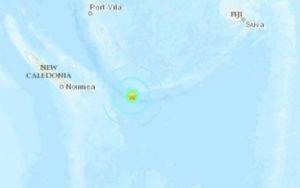Papua No. 1 News Portal | Jubi
Oleh Eleanor Ainge Roy di Tuvalu
Saat hari-hari yang panas, Leitu Frank merasa seperti ia tidak bisa bernapas lagi. Ibu rumah tangga dan ibu dari lima anak itu keluar dari rumahnya yang pengap, untuk mencari semburan angin di gubuk kayu sederhana di tepi laut.
“Laut menelan pasir,” kata Frank. “Sebelumnya, pasir pantai kita merentangkan jauh, dan saat kita berenang kita bisa melihat dasar laut, dan terumbu karang. Sekarang, air keruh sepanjang waktu, dan terumbu karang sudah mati. Tuvalu sedang tenggelam.”
“Tuvalu sedang tenggelam” adalah frasa yang umum mengenai dampak perubahan iklim di gugusan pulau kecil ini. Sebuah negara Polinesia yang terletak di Oseania, Tuvalu tidak lebih dari satu titik di tengah Samudra Pasifik.
Negara terkecil keempat di dunia, Tuvalu adalah rumah bagi 11.000 jiwa, yang sebagian besarnya tinggal di pulau terbesar, Fongafale, kota yang padat dimana mereka harus berjuang keras demi sedikit ruang. Luas daratan Tuvalu kurang dari 26 km persegi.
Sudah dua dari sembilan pulau di Tuvalu berada di ambang kehancuran, kata pemerintah, ditelan oleh naiknya permukaan air laut dan erosi pantai. Sebagian besar pulau di negara itu ketinggiannya hanya tiga meter di atas permukaan laut, dan pada saat air pasang yang paling tinggi, Fongafale membentang hanya 20 meter.
Saat badai, ombak menghantam pulau dari timur dan barat, “melahap” negara itu, menurut penduduk setempat.
Banyak yang berkata mereka dihantui mimpi buruk bahwa laut akan segera melahap mereka untuk selamanya, dan ini bukan ketakutan yang jauh dari kenyataan – mungkin bahkan generasi berikutnya. Ilmuwan memperkirakan Tuvalu tidak akan bisa lagi dihuni dalam 50 hingga 100 tahun mendatang. Warga setempat mengatakan mereka merasa waktunya lebih cepat dari itu.
Nausaleta Setani, bibi Frank, tidur di samping laguna di malam hari di bawah gubuk kayu, menggunakan sebuah pelampung sebagai bantal. Awalnya ia skeptis akan perubahan iklim, seperti banyak generasi tua di pulau itu, Setani perlahan-lahan percaya, setelah kehidupan sehari-harinya semakin sulit karena pergerakan laut yang tidak menentu.
UNDP menggolongkan Tuvalu sebagai negara miskin, terbelakang, yang “sangat rentan” terhadap dampak perubahan iklim.
Tanah yang berpori dan asin menyebabkan kesulitan di sepanjang pulau itu, dimana hampir tidak ada tanaman bisa dibudidayakan sama sekali, tanaman makanan pokok, pulaka, hancur dan hasil panen buah-buahan dan sayuran yang berkurang.
Makanan pokok Kepulauan Pasifik, seperti talas dan singkong, sekarang harus diimpor dengan biaya mahal, begitu juga dengan sebagian besar kelompok makanan lainnya.
Karena naiknya permukaan laut yang mencemari sumber air bahwa tanah, Tuvalu sekarang hanya bergantung pada air hujan, padahal musim kering juga semakin sering terjadi. Bahkan jika penduduk setempat berhasil menanam sesuatu, tidak ada air hujan yang cukup untuk menyirami bahkan kebun yang paling kecil.
Ikan juga, makhluk hidup di sini, pun dihindari masyarakat akibat keracunan biotoksin. Keracunan bahan Ciguatera disebabkan oleh ikan karang yang telah mencerna alga yang keluar akibat terumbu karang memutih. Ketika ikan yang terinfeksi racun Ciguatera ini dikonsumsi oleh manusia, ia menyebabkan response langsung dan kadang-kadang parah: muntah, demam tinggi, dan diare.
Di rumah sakit setempat, departemen khusus telah dibentuk untuk mempelajari dan menangani penyakit-penyakit yang muncul terkait perubahan iklim.
Sekitar sepuluh orang Tuvalu terkena keracunan ikan Ciguatera setiap minggunya, mencakup sekitar 10% dari penyakit terkait dengan iklim setiap minggunya. Suria Eusala Paufolau, dari rumah sakit setempat, mengatakan kasus keracunan ikan mulai melonjak kira-kira satu dekade lalu.
Penyakit lainnya terkait iklim yang juga meningkat mengikuti dampak perubahan iklim termasuk influenza, infeksi jamur, mata merah, dan demam berdarah, menurut penelitian rumah sakit itu.
Suhu udara yang lebih tinggi setiap hari juga membawa risiko dehidrasi dan sengatan panas, kata Paufolau.
“Apa pun yang terjadi,” tegas penduduk setempat berulang kali, mengutip perdana menterinya, “Tuhan akan menyelamatkan kita.”
Evakuasi adalah pilihan terakhir
Berbagai rencana untuk adaptasi perubahan iklim termasuk pembangunan tanggul laut.
Dewan kota setempat juga berencana untuk mereklamasi kembali daratan di selatan Fongafale, menaikkan permukaan tanah menjadi 10 meter di atas permukaan laut, dan membangun perumahan. Ini adalah rencana yang akan menelan biaya AS$ 206 juta, dan sejauh ini tidak ada yang bisa mendanai. Pilihan lain – seperti membangun pulau terapung – juga sedang dipertimbangkan.
Evakuasi dan meninggalkan pulau-pulau itu adalah pilihan terakhir, tegas Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga, meskipun ia sering kali membahas, dengan negara-negara tetangganya di Pasifik, bahwa warga Tuvalu akan menjadi pengungsi akibat perubahan iklim pertama di dunia.
Banyak pejabat pemerintah yang secara terbuka mengungkapkan kemarahan atas terpilihnya Donald Trump, menegaskan skeptisisme terhadap perubahan iklimnya telah menyebabkan kemunduran besar dalam hal kerja sama global menghadapi isu-isu perubahan iklim, dan membuat suara kecil Tuvalu di panggung dunia semakin mengecil.
“Saya rasa mereka membenci kita,” kata Soseala Tinilau Direktur Kementerian Lingkungan Hidup.
Sopoaga menegaskan kembali ‘tidak ada rencana B’ untuk Tuvalu, setiap upaya pemerintah berfokus pada beradaptasi dengan perubahan pola cuaca – dan tetap bertahan di sini.
Nikotemo Iona dari Biro Meteorologi Tuvalu berkata “banyak orang yang ingin bermigrasi sebagai respons terhadap perubahan iklim,” ia duduk di dalam kantornya yang kecil.
“Namun, sebagian besar dari generasi tua tidak ingin pindah karena mereka percaya mereka akan kehilangan identitas, budaya, gaya hidup dan tradisi mereka. Tetapi saya percaya generasi muda masih berniat untuk bermigrasi demi generasi mendatang.”
Duduk di atas batang pohon kelapa yang roboh, tatapan Enna Sione gelisah saat dia memandang lautan. Sione, suaminya, dan empat anaknya berencana untuk bermigrasi ke Selandia Baru dalam dua tahun ke depan.
“Cuaca telah benar-benar berubah. Kadang-kadang saya merasa takut pada lautan,” kata Sione, yang menambahkan bahwa dia terpaksa pergi demi anak-anaknya.
“Mungkin suatu saat Tuvalu akan lenyap. Dari apa yang saya lihat, banyak yang sudah hilang. Saya rasa suatu hari kita akan menghilang.” (The Guardian)
Editor: Kristianto Galuwo