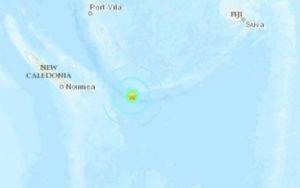Papua No. 1 News Portal | Jubi
Oleh Fuimaono Dylan Asafo
Tuila’epa Sailele Malielegaoi telah menjabat sebagai Perdana Menteri Sāmoa selama 21 tahun.
Ketika ia mulai memimpin pada November 1998, Tuila’epa memiliki tanggung jawab besar untuk membimbing orang-orang Sāmoa melangkah ke abad ke-21.
Dan ini bukanlah tugas yang mudah. Sebagai tertulis dalam memoarnya, Pālemia dengan tepat menyimpulkan:
“Kepemimpinannya telah marak dengan krisis politik dan ekonomi, bencana alam, perselisihan regional, dan persoalan-persoalan lokal. Karier politik Tuila’epa dimulai pada masa-masa sulit, tetapi ia telah menghasilkan suatu periode kestabilan politik dan perkembangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya melalui kepemimpinannya dalam memodernkan ekonomi, meningkatkan pendidikan & kesehatan, dan mengentaskan kemiskinan di Sāmoa.”
Meski pemerintahan Tuila’epa telah memungkinkan Sāmoa untuk memiliki kestabilan yang menyeluruh dan era pembangunan yang mantap, periode itu juga dipenuhi oleh banyak drama. Dari perseteruannya yang terkenal dengan Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, hingga tiga upaya pembunuhan yang berhasil dia hindari – menurut saya, semua orang Sāmoa setuju bahwa tidak pernah ada momen yang membosankan selama Tuila’epa memimpin.
Tuila’epa juga telah menunjukkan kepada kita bahwa dia tidak takut memimpin perubahan yang berani dan kontroversial atas perundang-undangan negara itu.
UU tahun 1998 untuk mengganti lalu lintas jalanan di Sāmoa dari sebelah kanan ke kiri, dan UU tahun 2011 untuk memajukan kalender Sāmoa satu hari lebih awal agar sama dengan Selandia Baru dan Australia telah membuktikan hal ini.
Namun sekarang, dengan amandemen konstitusi yang ia usulkan untuk membuat perubahan fundamental pada pengadilan khusus tanah dan hak kepemilikan tanah (Land and Titles Court; LTC), Tuila’epa sedang menghadapi perlawanan terbesar atas rancangannya.
Seperti banyak orang Sāmoa di seluruh dunia, saya juga menyaksikan dengan penuh perhatian semua kontroversi yang telah terjadi (dan masih akan terus terjadi) sedikit demi sedikit dengan dramatis. Tetapi hal yang menggemaskan tentang kontroversi politik ini adalah kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam membaca artikel-artikel dan menonton berita, dan pada akhirnya, masih tidak yakin siapa yang bisa dipercaya dan apa yang benar – terutama di era hoaks dan politik pascakebenaran.
Sebagai seseorang yang menghabiskan tahun terakhirnya di sebuah sekolah hukum di Amerika Serikat mempelajari Konstitusi AS, dan melihat pelanggaran yang dilakukan Presiden Trump terhadap Konstitusi setiap hari – saya sudah terbiasa dengan ketidakpastian yang besar seperti ini.
Namun, menurut saya, jika ada satu hal yang bisa kita pelajari dari drama di AS itu adalah, bahwa kita bisa memahami apa ‘kebenaran’ yang hakiki dengan memperhatikan bagaimana pemimpin-pemimpin memilih untuk menanggapi perselisihan pendapat dan kekhawatiran tentang perubahan hukum yang ingin mereka berlakukan.
Dengan kata lain, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri – saat dihadapkan dengan perlawanan, apakah pemimpin tersebut merendahkan diri dan lalu melibatkan diri dalam proses konsultasi dan debat yang demokratis untuk mencoba menyelesaikan masalah itu dengan iktikad baik? Atau, seperti Trump, apakah mereka lalu menyerang, menolak untuk mendiskusikan keprihatinan apapun, dan lalu melakukan serangan pribadi yang tidak ada hubungannya terhadap siapapun yang berani menantang mereka – menunjukkan tirani yang meresahkan?
Pemerintah yang demokratis atau tirani?
Menyaksikan situasi politik di Sāmoa saat ini – mulai dari Tuila’epa yang menyebut Wakil Perdana Menteri, Fiame Naomi Mata’afa, sebagai ‘setan’ dalam sidang parlemen, hingga melarang pengacara-pengacara di kantor Kejaksaan Agung Sāmoa untuk tidak menentang RUU amandemen konstitusi atau mengajukan keluhan apapun ke Sāmoa Law Society – tampaknya kita, sayangnya, sedang menyaksikan tipe tanggapan pemerintah yang kedua – tirani.
Oleh karena itu, sudah saatnya semua orang Sāmoa di luar negeri berbicara tentang bangktinya pemerintha yang tirani di Samoa, dan yang lebih penting, apa yang perlu dilakukan untuk mengakhirinya.
Arti tirani dari buku ‘On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century’ oleh Timothy Snyder, menjelaskan bahwa itu adalah praktik kekuasaan yang sewenang-wenang yang dipenuhi dengan ‘pembatasan kebebasan berpendapat; pembatasan atau peniadaan kebebasan sipil; UU yang disahkan oleh dekret tanpa debat publik atau persetujuan rakyat; penangkapan dan pemenjaraan tanpa pengadilan; penyiksaan dan pembunuhan oleh isntitusi pemerintah; dan pencurian, pemerasan, dan penggelapan oleh politisi yang berkuasa.”
Sampai saat ini, kontroversi di Sāmoa adalah pembatasan kebebasan berpendapat, dimana perintah Tuila’epa membungkam kantor Kejaksaan Agung sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Demikian pulang ketika Tuila’epa baru-baru ini memerintahkan kepada seorang MP dari partainya sendiri, Partai Perlindungan HAM (Human Rights Protection Party; HRRP), untuk mengundurkan diri setelah mereka menyuarakan perlawanan mereka terhadap amandemen pemerintah dalam pertemuan di dapil mereka.
Tetapi konflik saat ini adalah kekhawatiran akan pembatasan atau peniadaan kebebasan sipil dan pengesahan RUU tanpa debat publik atau persetujuan rakyat umum, setelah sejumlah pemimpin dan kelompok-kelompok yang maju untuk melawan amandemen yang diusulkan. Mereka yang menentang amandemen tersebut termasuk Ombudsman Sāmoa, sembilan Hakim Agung, dan hakim-hakim senior Peradilan Sāmoa, pengacara senior Sāmoa, Sāmoa Law Society, mantan Jaksa Agung Sāmoa, mantan Kepala Negara, kepala-kepala suku, Presiden New Zealand Law Society, dan lainnya.
Melihat daftar pihak yang keberatan itu, meski Tuila’epa dan Jaksa Agung yang baru saja mengundurkan diri, Lemalu Hermann Retzlaff, telah menyakinkan kita bahwa amendemen yang diusulkan itu telah dibenarkan dan bahwa kita tidak perlu khawatir – tingga jumlah oposisi dan keragamannya terhadap amandemen itu, dan tanggapan Tuila’epa, menunjukkan, jika tidak langsung membenarkan, bahwa kekuasaan yang tirani sedang digunakan.
Walaupun perhatian kita saat ini sedang fokus pada kontroversi amandemen LTC, kita juga harus mengingat bahwa ini bukan pertama kalinya Tuila’epa bertindak dengan tirani. Bahkan, jika ditelusuri lebih dalam, kita menemukan bahwa ada lebih banyak contoh besar dari pemerintahan tirani Tuila’epa di Sāmoa.
Salah satu contohnya adalah bagaimana Tuila’epa menangani krisis campak Sāmoa baru-baru ini. Sementara ada desakan dari dalam dan luar Pemerintah Sāmoa agar sebuah penyelidikan dimulai tentang bagaimana pemerintah mengelola wabah yang merenggut nyawa 81 anak itu, Tuila’epa telah menjelaskan mengapa ia menolak meluncurkan penyelidikan seperti itu. Ia mengatakan bahwa penyelidikan itu tidak diperlukan karena pemerintahnya tidak terlambat dalam melakukan program vaksinasi (seperti yang disinyalir oleh Kementerian Kesehatan Selandia Baru), dan bahwa sudah jelas wabah campak itu datang dari seorang pengunjung asal Selandia Baru.
Mantan Kepala Negara, Tuiatua Tupua Tamasese Efi, baru-baru ini menyatakan bahwa “reaksi Tuila’epa yang kuat untuk tidak membentuk Komisi Penyelidikan apa-apa menyiratkan kecemasan bahwa temuan komisi itu akan mengungkapkan kebenaran.” Kebenarannya adalah bahwa pemerintah Tuila’epa menolak untuk membiayai dukungan yang sangat diperlukan untuk epidemi campak setelah mereka memutuskan untuk menyewa pesawat untuk Sāmoa Airways.
Bukannya memberikan tanggapan langsung terhadap kekhawatiran Tuiatua, Tuila’epa justru memilih untuk menyerangnya secara pribadi, dengan berkata “mungkin orang tua itu tuli dan saya ragu dia menonton TV pengumuman publik tentang program vaksinasi.”
Contoh lain dari sikap tirani Tuila’epa adalah pengesahan UU pencemaran nama baik pada Desember 2017, yang mengkriminalkan kritik dan tuduhan yang dilayangkan terhadap dirinya.
Cendekiawan bidang hukum, Beatrice Tabangcora, telah menemukan beberapa isu dengan pengesahan UU ini, termasuk: absennya konsultasi publik sebelum pengesahan RUU (karena Tuila’epa menolak melakukannya); fakta bahwa biaya yang akan dibelanjakan jika Tuila’epa menuntut siapapun di bawah hukum itu akan ditanggung oleh masyarakat; dan pelanggaran UU akan hak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.
Seperti yang diharapkan, ketakadilan dari hukum ini terlihat pada Oktober 2019, dimana Malele Paulo atau ‘King Faipopo’ ditahan selama tujuh minggu karena menuduh Tuila’epa, melalui Facebook, terlibat dalam berkomplot untuk membunuh pamannya. Menurut pengamatan akademisi studi politik, Jope Tarai, pemenjaraan Paulo adalah kasus pertama di Pasifik dimana seseorang dipenjarakan karena menuliskan komentar negatif di media sosial, dan bahwa hukuman itu merupakan ‘preseden yang meresahkan untuk kebebasan berpendapat di Sāmoa dan Pasifik.’
Satu lagi contoh baru-baru ini bukti adanya tirani di Sāmoa adalah amandemen konstitusi untuk menyatakan Sāmoa sebagai negara Kristen pada Juni 2017. Tuila’epa dan Retzlaff mengklaim bahwa amandemen tersebut merupakan pengakuan komitmen Sāmoa terhadap kekristenan yang yang tidak berbahaya. Namun, ahli hukum lainnya, Dr. Bal Kama, dan analis politik, Grant Wyeth, telah menunjukkan bahwa ada motivasi Islamofobia yang dinormalkan Trump di balik hukum itu, yang telah disusun oleh rasa takut yang tak berdasar atas ekstremisme Islam di Sāmoa.
Selanjutnya, klaim Tuila’epa dan Retzlaff bahwa amandemen tersebut dilakukan untuk mengakui pentingnya agama Kristen di Sāmoa bisa dibantah dengan diberlakukannya UU untuk memberlakukan wajib pajak kepada semua pendeta gereja pada Juni 2018. Sekali lagi, meski beberapa pihak mungkin setuju dengan pendapat umum bahwa pendeta gereja harus membayar pajak, pihak yang menentang UU itu menegaskan bahwa UU itu disahkan tanpa konsultasi publik yang memadai, dan bahwa hukum itu melanggar perlindungan Konstitusi atas agama Kristen – perlindungan yang diharuskan dengan amandemen negara Kristen satu tahun sebelumnya.
Kontroversi yang sedang berlangsung saat ini mengenai amandemen konstitusi dan contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa kita perlu memikirkan bagaimana menghadapi pemerintah yang bersikap tirani di Sāmoa.
Fuimaono Dylan Asafo adalah dosen hukum di Fakultas Hukum di University of Auckland, dan memegang gelar Magister Hukum dari Universitas Harvard dan University of Auckland. (RNZI)
Editor: Kristianto Galuwo