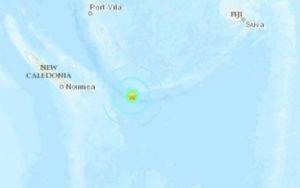Papua No. 1 News Portal | Jubi
Oleh Dan McGarry
‘Kevakuman hanya akan membuka kesempatan bagi orang lain untuk mengisinya.’
Pengamatan itu diungkapkan oleh seorang Anggota Parlemen (MP) Vanuatu, MP Johnny Koanapo, di Facebook baru-baru ini. MP anggota dari kubu oposisi itu dulunya merupakan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri, dan telah berperan penting dalam sejumlah negosiasi bilateral dan multilateral.
MP Koanapo menulis sebuah tulisan di Facebook sebagai protes yang sopan namun tegas, dalam menanggapi pernyataan Duta Besar Amerika Serikat, Catherine Ebert-Gray, kepada ABC bahwa pemerintah Amerika merasa “sangat kecewa” pada keputusan pemerintah Kepulauan Solomon, untuk mengalihkan hubungan diplomatiknya dari Taiwan ke Tiongkok. Ebert-Grey ditunjuk untuk menjadi duta besar negaranya di Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.
Komentar MP Koanapo itu mirip dengan sentimen yang dipercayai secara meluas di Pasifik. Pemerintah AS mungkin kecewa, tetapi seharusnya mereka tidak terkejut, katanya. Mereka “hanya perlu meningkatkan kehadiran mereka di sini di setiap saat, dan bukan hanya selama masa perang. Mereka tidak bisa hanya terus memiliki kehadiran melalui perwakilan saja di sini.”
Strategi Amerika yang selalu ‘mendelegasikan’ keterlibatannya dengan negara-negara Pasifik Barat, baik kepada Taiwan atau Australia – mantan PM Australia John Howard bahkan pernah ia dicap sebagai ‘wakil’ Amerika di Pasifik – berarti ia tidak akan pernah bisa mencapai tujuannya, tegas Koanapo.
Australia dan Selandia Baru juga belum terbukti dapat menjadi reseptif atau responsif terhadap kebutuhan pembangunan negara-negara tetangga mereka di Pasifik. Harapan orang-orang Kepulauan Pasifik akan bantuan sering kali dengan semena disebut sebagai serakah, egois, ketidakberdayaan, atau bahkan malas. Komentar mantan menteri lingkungan hidup Australia, Melissa Price, kepada mantan Presiden Kiribati, Anote Tong, “Saya punya buku cek saya di sini. Berapa banyak uang yang Anda inginkan?”, sebagai salah satu contoh. Kejadian itu hanya menunjukkan betapa besarnya jurang pemisah antara nilai-nilai tradisional Pasifik dan individualisme negara-negara Barat.
Di sebagian besar budaya-budaya Kepulauan Pasifik, sangat tidak terbayangkan kalau ada orang-orang yang kurang beruntung, yang harus terus menderita sedangkan yang lain terus maju dan berkembang. Sudah jelas kita harus membantu mereka yang kurang beruntung. Pada 1980-an, Pastor Walter Lini menyebut prinsip itu sebagai Sosialisme Melanesia atau ‘Melanesian Socialism’, tetapi ini lalu disalahartikan oleh prajurit yang terlibat dalam Perang Dingin, mereka tidak menyadari bahwa penekanan prinsip ini adalah pada kata Melanesia, bukan yang satunya. (Ini sangat ironis. Akibat Lini, Vanuatu terdaftar dalam Gerakan Non-Blok. Vanuatu masih menjadi anggota NAM hingga saat ini).
Banyak pihak yang mengomentari suasana tidak pasti yang diciptakan oleh momen transformasional ini, menyusul beralihnya Kepulauan Solomon, dan potensi adanya konsekuensi jangka panjang dalam politik dalam negeri Kepulauan Solomon. Tetapi Koanapo percaya bahwa “suatu titik keseimbangan akan dicapai pada waktunya. Pada saat itu kita akan memiliki keadaan ‘normal’ baru.”
Seharusnya tidak ada yang terkejut dengan semua perkembangan ini, tambahnya.
“Pilihan ini telah bergolak selama beberapa tahun terakhir, dan jika teman-teman kita merasa bahwa sinyal ini tidak kuat atau tidak cukup berarti, itu artinya ada terlalu banyak ketakpedulian atau tidak ada yang peduli.”
Dia bukan satu-satunya yang mengamati hal ini. Dalam laporan yang diterbitkan oleh ABC baru-baru ini dinyatakan bahwa peralihan tersebut, secara efektif, dibeli oleh Tiongkok dari Kepulauan Solomon dengan tawaran bantuan sebesar $ 730 juta dalam pembiayaan infrastruktur, pernyataan ini benar-benar mengabaikan satu poin penting. Itu adalah katalisator, namun bukan penyebab.
Seperti yang dikatakan Koanapo, ia memiliki alasan untuk percaya bahwa politisi-politisi Kepulauan Solomon, sudah lama merasa peralihan ke Tiongkok itu tidak dapat dihindari. Tidak ada imbauan dari Amerika Serikat, Australia, atau mitra lainnya, yang bisa meyakinkan mereka bahwa Tiongkok tidak akan menjadi kuasa ekonomi dan politik yang dominan di Pasifik, dalam satu dekade ke depan.
Politisi-politisi ini dihadapkan dengan dua pilihan: beralih sekarang, dan mendapatkan penawaran yang lebih baik dari yang pernah ditawarkan Taiwan. Atau nanti, dengan rendah diri.
Ini bukan permainan zero-sum bagi negara-negara Kepulauan Pasifik. Analis-analis politik Barat sering mengabaikan mantra bahwa negara-negara Pasifik lebih memilih untuk menjadi teman bagi semua, tidak menjadi musuh dari siapa pun. Setiap kali garis itu dilewati oleh orang-orang Barat, ini lalu diikuti oleh kedipan mata dan senggolan di bahu, seolah berkata, “Tapi mereka masih lebih menyukai kita.”
Hal seperti itu seharusnya tidak dibiarkan, dan bahkan ketika itu dilakukan, itu tidak boleh dianggap remeh. Koanapo menulis: “Mengapa teman-teman kita lebih berhati-hati terhadap Tiongkok tanpa meminta Prancis untuk mendekolonisasikan wilayah-wilayah kedaulatan kita di Pasifik? Mereka mengambil tanah kita dan masih menempati ruang kita. Tidak ada yang berpikir bahwa dengan meremehkan kedaulatan kita, mereka mengganggu perdamaian kita dan membuat kita terlihat lebih rentan.”
Ia lalu menyimpulkan: “Biarkan Kepulauan Solomon membangun hubungan mereka dengan Tiongkok, karena mungkin dengan inilah mereka dapat memperluas peluang pembangunan mereka. Kita akan melihat lebih banyak keadaan-keadaan ‘normal’ yang baru di tahun-tahun mendatang.” (The Interpreter by Lowy Institute)
Editor: Kristianto Galuwo