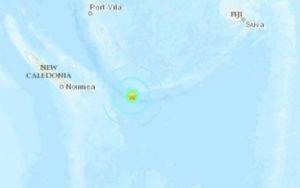Papua No.1 News Portal | Jubi
Oleh Joshua McDonald
Hujan terakhir yang memadai di Banaba terjadi lebih dari setahun yang lalu. Tanpa hujan, orang-orang di pulau di kawasan Pasifik tengah yang terisolasi, bagian dari negara Kiribati, terpaksa hanya bisa mengandalkan desalinasi air laut untuk semua kebutuhan sehari-hari mereka, mulai dari minum, mandi, dan bercocok tanam.
Namun pada akhir November, pabrik desalinasi air itu rusak dan situasi bagi hampir 300 orang yang tinggal di sana menjadi sangat mengenaskan. Kisah-kisah yang meresahkan mulai muncul tentang orang-orang yang terpaksa minum air yang terkontaminasi, terserang wabah penyakit, dan ketakutan akan kelaparan.
“Penyakit kulit dan diare tersebar luas, terutama pada anak-anak, karena kami tidak punya pilihan selain minum air yang terkontaminasi atau air asin,” ungkap seorang warga Banaba, Taboree Biremon. “Anak-anak mereka tidak mengerti. Mereka ingin memakan makanan yang tidak dapat mereka dapatkan. Kami merasa sangat sedih tentang hal itu, tetapi tidak ada apa-apa yang bisa kami lakukan.”
Selama tiga bulan warga di Banaba tidak punya air bersih untuk diminum, tidak ada makanan selain ikan karena semua tanaman mereka mati, dan mereka tidak bisa mandi, kata Taboree.
“Kami juga tidak bisa tidur, karena yang ingin kami lakukan hanyalah mencari air di pulau itu. Kami hanya mencari cara untuk bisa bertahan hidup. Perasaan kita bagaikan hanyut di laut, tersesat, dan tidak ada yang peduli.”
Sebuah kapal dari ibu kota Kiribati, Tarawa, 400 km jauhnya, akhirnya sampai pada bulan Maret, mengantarkan air kemasan dan peralatan untuk membangun pabrik desalinasi baru.
Tetapi tetua-tetua di Banaban percaya bahwa hanya mengandalkan dukungan dari tempat-tempat yang jauh itu tidak berkelanjutan, terutama karena krisis iklim semakin memburuk.
“Pabrik desalinasi bukanlah solusi,” tekan Roubena Ritata, seorang tetua. ”Berapa lama lagi sampai peralatan yang ini rusak dan kita kembali ke situasi yang sama? Yang kami perlukan adalah rehabilitasi pulau kami.”
Pemimpin-pemimpin Banaba sedang mencari solusi jangka panjang. Bahkan, mereka mencari solusi yang akan memungkinkan mereka kembali menggunakan cara-cara tradisional dalam menampung dan mengumpulkan air, metode yang memungkinkan nenek moyang mereka bertahan hidup di pulau itu selama berabad-abad sebelumnya.
Untuk mencapai keinginan ini, para tetua menyurati pemerintah Australia dan Selandia Baru, meminta dukungan kedua negara untuk membangun kembali atau membersihkan jaringan gua bawah tanah yang suci, yang dikenal sebagai te bangabanga.
Australia dan Selandia Baru telah turut menyebabkan perusakan te bangabanga sepangjang abad ke-20 melalui penambangan fosfat, yang dimulai oleh penambang asal Australia Albert Ellis pada 1900.
Selama 80 tahun sejak itu, British Phosphate Commission, yang merupakan milik bersama Australia, Selandia Baru, dan Inggris, menambang Banaba dengan begitu ekstensif sehingga sekitar 90% permukaan pulau itu ditelanjangi. Pada saat BPC pergi, 22 juta ton tanah telah dipindahkan.
“Pengrusakan itu benar-benar merupakan akibat dari aktivitas mereka,” tegas Katerina Teaiwa, seorang akademisi asal Banaba, profesor madya di Australian National University, dan penulis buku ‘Consuming Ocean Island: Stories of People and Phosphate from Banaba’. “Mereka sampai, mengadakan pesta besar-besaran, menghasilkan banyak uang, dan pergi begitu saja.”
Mungkin hal yang paling disesalkan adalah dampak penambangan itu terhadap te bangabanga. Berdasarkan sejarahnya, orang-orang Banaba mampu bertahan dari kekeringan karena kemampuan alami gua itu untuk menampung air.
Tetapi menurut para tetua, hampir semua gua sudah hancur, beberapa yang tersisa pun telah terkontaminasi.
“Bagi banyak orang Banaba, te bangabanga sekarang hanya ada dalam cerita-cerita daerah dan tarian yang diturunkan dari generasi ke generasi,” tutur seorang tetua, Pelenise Alofa, menambahkan bahwa menurut sejarahnya, hanya perempuan yang bisa memasuki gua-gua itu, yang menekankan pentingnya perempuan dalam masyarakat itu. “Tapi Itu semua sekarang telah hilang….”
“Kami menari-nari dan menceritakan kisah bagaimana nenek moyang kami menemukan gua itu saat musim kemarau yang sangat kering. Itu adalah bagian dari identitas kita, saya pikir masalah ini sudah akan terselesaikan sekarang – malah ini menjadi semakin buruk.”
Alofa menerangkan para tetua ingin Australia dan Selandia Baru mendanai sebuah tim peneliti untuk melakukan pergi ke Banaba dan menilai kerusakan yang ada serta memulihkan lingkungan gua.
Masyarakat Banaba sudah berupaya sebelumnya untuk mengklaim kompensasi atas apa yang dilakukan di atas tanah mereka – ini membuahkan beberapa kemenangan kecil. Pada 1976, sebuah kelompok menggugat Inggris atas keterlibatannya dalam kerusakan tadi: pengadilan memutuskan bahwa meski Inggris memiliki utang secara moral, ia tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi.
Pemerintah Inggris akhirnya menawarkan pembayaran ex gratia sebesar AS$10 Juta atas nama pemerintah-pemerintah pemilik BPC kepada masyarakat Banaba dengan syarat mereka membatalkan semua tuntutan hukum selanjutnya.
Sekarang orang-orang Banaba mengatakan kekeringan yang melanda telah memperkuat tekad mereka untuk kembali mencari kompensasi dan solusi jangka panjang.
Meski Banaba saat ini hanya ditinggali oleh 300 orang, itu memiliki jumlah diaspora hampir 6.000 jiwa. Kebanyakan orang Banaba dipindahkan secara paksa ke pulau Rabi di Fiji ketika penambangan dimulai kembali menyusul jeda selama perang dunia kedua.
“Setiap orang Banaba di Fiji dan komunitas diaspora kami di Auckland berkeinginan untuk kembali ke Banaba dan berhubungan kembali dengan tanah air kami, tetapi kehancuran yang disebabkan oleh pertambangan itu menyebabkan tidak ada lagi tempat bagi orang-orang untuk menetap,” kisah Rae Baineti, seorang pemimpin pemuda dan direktur Kiribati Auteroa Diaspora Directorate.
Dia menambahkan: “Sebagai seorang aktivis, saya mengajar generasi muda untuk mengadvokasikan diri mereka dan berani. Saya mendorong mereka untuk melakukan percakapan seperti ini, untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah yang menyebabkan kerusakan di tanah kami.”
Dampak lain dari penambangan adalah pembangunan tempat tinggal menggunakan asbes, yang bila dihirup untuk periode yang lama dapat menyebabkan kanker paru-paru dan mesothelioma, keduanya penyakit mematikan.
Mike McRae-Williams, seorang spesialis lingkungan hidup dari Australia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di sektor pertambangan, pada 2008n lalu dikontrak untuk pergi ke Banaba untuk menilai keparahan situasinya. “Kesimpulan kami adalah bahwa itu sangat serius,” ungkapnya. “Ini jelas-jelas merupakan bahaya bagi kesehatan orang-orang yang tinggal di sana, mereka akan mengalami dampak kesehatan yang signifikan. Saya tidak yakin sudah ada apapun yang dilakukan tentang hal itu.”
Katerina Teaiwa menekankan bahwa desakan orang-orang Banaba akan rehabilitasi tanah harus diperhatikan: “Kita perlu menjauh dari narasi yang sudah lama ada tentang ‘orang Banaban yang miskin, yang tidak memiliki air, membantu mereka’ dan bergerak menuju pendekatan yang benar-benar berfokus pada solusi.
“Semua ini adalah rangkaian krisis. Kita tidak bisa terus-menerus menceritakan kisah tentang kehancuran dan kerentanan berulang-ulang kali. Bagaimana krisis berakhir, jika tidak dengan keadilan?” (The Guardian)
Editor: Kristianto Galuwo