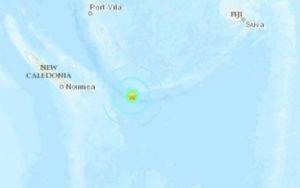Papua No. 1 News Portal | Jubi
Oleh Mata’afa Keni Lesa
Kematian Perdana Menteri Tonga ‘Akilisi Pōhiva, Kamis pekan lalu (12/9/2019), adalah kehilangan yang besar bagi kita semua.
Kepergiannya bukan hanya menyusahkan hati mereka di Kerajaan Tonga, negara di mana dia telah membawa dampak demokrasi yang luar biasa, namun kematiannya sedang diratapi di seluruh dunia oleh kaum pemikir bebas dan orang-orang yang memperjuangkan kebebasan, transparansi, demokrasi, dan masalah-masalah penegakan HAM, di mana Pōhiva adalah salah satu dari mereka.
Sampai tiba ajalnya, Pōhiva masih bersuara. Bagaimana bisa kita melupakan desakannya yang berapi-api tentang perubahan iklim, ketika dia dilaporkan oleh berita-berita utama menangis saat pertemuan pemimpin-pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) terakhir di Tuvalu, di mana isu itu menjadi topik hangat?
Dan bagaimana saat dia dengan berani maju untuk berbicara dengan penuh keyakinan, dalam menyoroti penderitaan orang West Papua selama pidatonya baru-baru ini di hadapan Sidang Umum PBB di New York? Di saat banyak pemimpin Pasifik menghindari membahas isu kontroversial itu, Pōhiva tidak terintimidasi. Dia mengungkapkan pandangannya dan tidak segan-segan dalam menggunakan pengaruhnya untuk menarik perhatian pada persoalan ini.
Ini adalah jati diri seseorang yang lahir untuk memperjuangkan kebebasan, keadilan, moralitas, dan melakukan apa yang adil dan benar, tidak hanya untuk negaranya sendiri, tetapi juga bagi setiap jiwa yang hidup di permukaan bumi ini.
Tidak peduli apa pun persoalannya, Pōhiva bisa selalu menjadi andalan kita dalam membela suara rakyat kecil, yang kalau tidak diwakilkan akan diabaikan begitu saja oleh mereka yang berkuasa dan berpengaruh. Inilah yang telah hilang di Tonga dan wilayah ini, tentang pejuang Pasifik ini.
Karena hal ini juga, maka kematiannya adalah saat yang sangat memedihkan bagi mereka yang mengagumi keberaniannya yang tidak pernah padam, dalam berjuang melawan sistem dan korupsi. Dalam iklim politik, ekonomi, dan sosial dewasa ini, orang-orang seperti Pōhiva ini jarang kita temui. Mengapa? Orang-orang ingin menjadi populer dan disukai banyak orang; mereka ingin dilihat bersanding dengan orang-orang penting dan berpengaruh; mereka tidak ingin mengusik sistem yang berlaku.
Pōhiva bukan salah satu dari mereka. Dia menjalani tiga dekade di Parlemen Tonga hanya untuk memperjuangkan demokrasi di Tonga. Dia berdiri dan melawan sistem monarki Tonga, yang sudah pasti memerlukan keberanian yang luar biasa. Dia pernah ditahan, bahkan digugat dengan tuduhan penghasutan (sedition) pada suatu waktu, tetapi dia tidak pernah menyerah, dia tetap bertahan dan melawan.
Tidak mengejutkan melihat ramainya dukungan dari seluruh dunia setelah kematiannya di Auckland pekan lalu.
Pada usia 78, Pōhiva telah menghadapi berbagai masalah kesehatan untuk beberapa waktu, tetapi ia menolak untuk membiarkan masalah kesehatannya, untuk menghentikan ia dari melakukan apa yang ia rasa harus ia lakukan.
Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, termasuk salah satu orang pertama yang menuliskan penghormatan kepadanya. ‘Dia adalah pejuang yang bertekad kuat untuk rakyatnya, untuk Tonga, dan keluarga Pasifik tercinta kita,’ tulis Morrison. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, memuji ‘komitmennya untuk memperjuangkan demokrasi seumur hidupnya.’
Namun rekannya dari Fiji, PM Frank Bainimarama, menuliskan salah satu pesan penghormatan terbaik yang pernah ditulis tentang Pōhiva, bahwa ia telah ‘menginspirasi dunia ini dengan emosi yang menyentuh,’ merujuk pada pendiriannya tentang isu perubahan iklim. ‘Kita harus menghormati reputasi yang ia tinggalkan dengan melanjutkan perjuangan ini,’ kata Bainimarama.
Kita sangat setuju dengan sentimen seperti ini. Komitmen Pōhiva dalam menyuarakan isu-isu yang umumnya dijauhi orang lain – termasuk keadilan, transparansi, demokrasi, dan kebebasan – hal-hal ini yang akan diingat sebagai warisannya di Tonga, di Pasifik, dan di seluruh dunia.
Dia mungkin tidak akan diingat sebagai Perdana Menteri Tonga. Akan selalu ada perbedaan pendapat mengenai apakah dia benar-benar membawa perbedaan besar dalam hal pembangunan, dan apakah posisi pro-demokrasinya memajukan Kerajaan Tonga di bawah kepemimpinannya.
Seperti banyak pejuang bebas lainnya yang pernah kita lihat di seluruh dunia, yang berjuang sangat keras melawan sistem dan status quo, Pōhiva harus berjuang keras untuk memungkinkan transisi Tonga ketika ia menjadi Perdana Menteri.
Hal ini dapat dimengerti. PM Pōhiva sendiri tidak dapat melawan siapa pun selain dirinya sendiri dan pemerintahannya. Dia telah berubah menjadi sistem dan status quo dan tidak ada lagi yang bisa dia lawan selain dirinya sendiri. Beberapa contoh dari hal ini dapat disaksikan dalam pengambilan keputusannya di masa lalu yang mencerminkan hal ini. Hal ini mungkin telah sedikit menodai reputasinya.
Namun ini juga adalah pengingat bagi kita semua, bahwa seberapa pun hebatnya seseorang, mereka adalah manusia.
Saat ini adalah saat berduka di Tonga dan di Pasifik. Wilayah ini telah kehilangan seorang pejuang, seorang pejuang yang berani.
Dalam kisahnya yang diterbitkan oleh Kaniva Tonga News, ‘Akilisi Pōhiva menghabiskan hidupnya dengan berpindah dari rumah ke rumah sepanjang hidupnya, baik rumah saudara perempuannya, saudara laki-lakinya atau anak-anaknya sendiri.
Ketika dia meninggal dunia, dia tidak memiliki rumah atau tanahnya sendiri.
Ia sering diejek saat berkampanye untuk memimpin negara, ketika dia tidak bisa membeli tanah dan membangun rumah untuk keluarganya.
Dalam konteks Tonga, ejekan seperti itu sangat menghina.
Politisi veteran itu pernah bergurau bahwa yang paling penting baginya untuk memiliki ‘tanah’ di surga, kata anak sulungnya Siaosi Pōhiva.
Putrinya, Lautala Tapueluelu, memposting tulisan mengenai ‘Akilisi di Facebook pekan lalu, dengan mengatakan ayahnya mengutamakan orang-orang Tonga daripada anak-anaknya sendiri.
Putranya, Po’oi Pōhiva, pernah berkata kepada Kaniva bahwa dia percaya ayahnya dilahirkan untuk membantu membawa demokrasi ke Tonga.
Ketika dia masih muda, tugas ‘Akilisi setiap pagi adalah pergi memancing dengan pamannya dengan sampan.
Ketika ‘Akilisi menghadiri sekolah menengah di sekolah berasrama, Tupou College, tidak ada orang lain yang membayar uang sekolahnya.
Dia belajar dan belajar, dan pada saat libur dia akan berjalan ke desa terdekat di Malapo untuk mengumpulkan jamur talingelinga, dan menjualnya ke usaha-usaha lokal untuk membayar biaya sekolahnya. (Samoa Observer)
Editor: Kristianto Galuwo