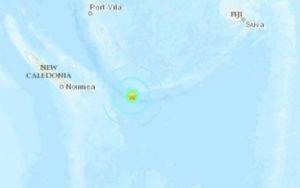Papua No.1 News Portal | Jubi
Oleh Sheldon Chanel
Sebagian besar negara Fiji dipaksa untuk tetap tinggal di dalam rumah akibat berbagai karantina wilayah dan pembatasan jam malam tingkat nasional Maret tahun lalu, ketika negara kepulauan di Pasifik Selatan itu mengumumkan kasus Covid-19 yang pertama.
Langkah yang sigap dan tegas dari legislator negara tersebut berhasil membantu mengendalikan penyebaran virus Corona, dan mereka pun menerima pujian dari komunitas internasional.
Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut telah meninggalkan bekas yang dalam pada negara itu.
Kelompok-kelompok masyarakat sipil mengatakan bahwa isolasi sosial terbukti jauh lebih berbahaya bagi banyak perempuan di negara itu daripada virus mematikan yang menanti mereka di luar rumah.
Aktivis dan organisasi-organisasi non-pemerintah melaporkan adanya ‘peningkatan yang mengkhawatirkan’ dalam hal angka kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan sejak pandemi dimulai di negara di mana tingkat KDRT-nya sudah termasuk salah satu yang tertinggi di dunia.
“Ini (pandemi) sudah pasti telah meningkatkan (kekerasan terhadap perempuan), dibandingkan antara 2019 dengan tahun lalu – frekuensi dan intensitasnya telah meningkat,” ungkap Shamima Ali, koordinator pusat krisis perempuan dan anak di Fiji, Fiji Women’s Crisis Centre (FWCC).
“Kasus pemukulan semakin parah – ada yang dipukul dan ditendang, ini dari dulu sudah dilaporkan, tapi ada juga penggunaan senjata tajam seperti pisau, dan kasus prostitusi dengan paksa terhadap perempuan dan anak.”
Kawasan Pasifik, rumah bagi 0,1% populasi dunia, memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan tertinggi secara global.
Sebelum pandemi, rata-rata 30% perempuan di seluruh dunia pernah mengalami beberapa bentuk kekerasan fisik atau seksual, kebanyakan oleh pasangannya, menurut data PBB.
Angka tersebut dua kali lipat di Fiji, dimana sekitar 64% perempuan mengatakan bahwa mereka pernah menjadi korban dari lebih dari satu bentuk kekerasan. Jumlahnya sama tinggi dengan negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya, termasuk Kiribati (68%), Kepulauan Solomon (64%) dan Vanuatu (60%).
Meskipun belum dilakukan penelitian untuk menentukan tingkat KDRT pasca-Covid-19 di Fiji, tanggapan dari kelompok perempuan, ditambah dengan perkembangan yang terjadi di negara lainnya, mengindikasikan situasi yang suram, dipicu oleh naiknya angka pengangguran dan kemiskinan yang menyertai pandemi ini.
Para ahli menggambarkan ini sebagai sebuah krisis di tengah-tengah krisis lainnya, dan memperingatkan bahwa kecuali tindakan yang tegas segera diambil, tatanan sosial di wilayah tersebut terancam.
Jaringan layanan bantuan nasional bebas pulsa FWCC mencatat peningkatan 300% dalam panggilan terkait KDRT satu bulan setelah pembatasan jam malam dan karantina wilayah diumumkan, termasuk 527 panggilan pada April 2020, dibandingkan dengan 87 panggilan pada Februari dan 187 keluhan pada Maret.
Meskipun karantina wilayah sudah tidak terlalu ketat, pembatasan jam malam – dari pukul 11 malam hingga 4 pagi setiap malam – masih berlaku.
‘Pandemi bayangan’
Menurut laporan PBB, semua jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan telah meningkat di seluruh dunia selama pandemi ini. PBB menyebutkan ‘Pandemi bayangan’.
Ali mengatakan akar penyebab kekerasan adalah budaya patriarki yang merajalela dan mengakar di seluruh masyarakat Fiji, dimana perempuan dipandang sebagai ‘warga kelas dua’.
“Dan kemudian ada faktor tambahan tentang masalah agama, yang sifatnya juga sangat patriarki. Kita memiliki kepercayaan yang dalam dan kita sangat menghormati agama, ini sering digunakan untuk menindas perempuan,” jelas Ali.
Pemicu KDRT yang sudah ada sebelumnya saat ini semakin buruk oleh tekanan yang disebabkan oleh dampak sosial ekonomi dari pandemi.
Dengan populasi 900.000, Fiji adalah ekonomi terbesar kedua di Pasifik, dan negara tujuan pariwisata yang populer.
Turunnya perjalanan internasional dan lesunya industri pariwisata secara global menyebabkan lebih dari 115.000 orang kehilangan pekerjaan mereka di negara itu, serta ekonomi yang melemah secara keseluruhan mencapai 21% pada 2020.
Dampak yang paling signifikan terjadi di bagian barat negara itu, yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Di daerah itu terletak hotel-hotel internasional seperti The Marriott Fiji Resort, Sheraton Fiji, dan Radisson Blu Resort berada.
Sashi Kiran, pendiri dan direktur yayasan Foundation for Rural Integrated Enterprises and Development (FRIEND) di Fiji, mengatakan laki-laki mengalami sulit dalam mengelola perasaan stres akibat kehilangan pekerjaan, yang lalu menyebabkan KDRT dan masalah-masalah sosial lainnya.
Kombinasi antara stres terkait pengangguran dan isolasi sosial, ditambah dengan kurangnya akses perempuan pada sistem peradilan, telah menciptakan kondisi yang optimal untuk meningkatkan kasus KDRT, tambahnya.
Nalini Singh, direktur eksekutif Fiji Women’s Rights Movement (FWRM), mengatakan peningkatan KDRT itu bukan hal yang baru. Krisis-krisis yang terjadi sebelumnya memang cenderung lebih memengaruhi perempuan dan anak perempuan, menurutnya.
“Ini telah menjadi kekhawatiran yang besar bagi kami, karena kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan sudah menjadi pandemi bayangan di Fiji; Covid-19 hanya memperburuk situasi ini,” tegas Singh.
Rajni Chand, ketua dewan FemLINK Pacific, sebuah organisasi media feminis regional yang bekerja dengan perempuan di daerah pedesaan, mengatakan isolasi sosial telah meningkatkan jumlah dan mengintensifkan kekerasan di belakang pintu rumah-rumah.
“Perempuan itu terisolasi secara sosial, di rumah yang dikarantina, dan pelaku kekerasan juga dikarantina ditempat yang sama,” katanya.
Kekerasan yang dialami perempuan dan anak perempuan di rumah juga menyulitkan partisipasi ekonomi dan politik mereka, di wilayah di mana perempuan selama ini kurang terwakili dalam kedua sektor tersebut.
Sebuah jurnal pada 2015 tentang KDRT dan prevalensinya di negara berkembang pulau kecil (SIDS) menemukan bahwa kerugian yang disebabkan oleh KDRT terhadap ekonomi Fiji adalah 6,6% dari produk domestik bruto (PDB).
Baru-baru ini, sebuah laporan yang disusun oleh National Democratic Institute menemukan bahwa tingkat KDRT yang di Fiji, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon yang melambung turut menghalangi partisipasi perempuan dalam dunia politik.
Pemerintah pusat dan regional, serta organisasi-organisasi masyarakat sipil, telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Pada 2018, Uni Eropa, pemerintah Australia, PBB, Komunitas Pasifik (SPC), dan Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik (PIF) meluncurkan proyek Pacific Partnership to End Violence against Women dengan nilai AU$ 27,5 juta.
Capaian utama dari proyek lima tahun ini adalah untuk mempromosikan norma-norma kesetaraan gender melalui pendidikan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, serta memberdayakan masyarakat sipil di tingkat nasional dan regional.
Solusi jangka panjang untuk mengatasi patriarki
Kementerian Perempuan Fiji juga mengadakan sejumlah konsultasi nasional untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional dengan melibatkan seluruh pemerintah dan komunitas untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
Namun Covid-19 semakin memperparah tantangan yang sudah ada sebelumnya. Sekarang ada desakan agar inisiatif-inisiatif seperti ini juga memadukan pendekatan yang lebih holistik – akibat pandemi ini – dan capaian-capaian yang lebih spesifik ke perempuan.
“Saat ini, ada banyak penekanan pada menghidupkan kembali ekonomi daripada melanjutkan pekerjaan yang dilakukan sebelum pandemi,” ungkap Shamima Ali dari FWCC. “Fiji sangat beruntung karena kami memiliki gerakan feminis yang kuat, dan kami bersuara untuk memastikan perempuan dilibatkan dalam perencanaan ekonomi, tetapi negara-negara lain di kawasan ini tidak memiliki gerakan-gerakan seperti ini.”
Ali menambahkan bahwa Fiji memiliki sejumlah UU KDRT yang progresif, termasuk perintah perlindungan KDRT dan Kebijakan No-Drop, yang berarti pihak berwenang akan melakukan penyidikan bahkan jika seorang perempuan mencabut tuntutannya atau ada rekonsiliasi.
“UU ini sukses dalam banyak kasus; tapi itu juga tidak bekerja akibat sikap pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya,” jelasnya. “Ada banyak pihak yang mengatakan hal-hal yang benar, tetapi bagaimana hal itu sebenarnya terjadi di dalam sistemnya – pengadilan, kantor polisi, dan layanan kesehatan – itu sangat berbeda dan jarang melindungi perempuan.”
Nalini Singh dari FWRM percaya bahwa diperlukan sebuah solusi jangka panjang untuk mengatasi akar penyebab kekerasan berbasis gender – patriarki – dan mendorong laki-laki untuk mengubah sikap dan perilaku mereka.
“Penting juga untuk mengalokasikan sumber daya khusus selama pandemi untuk menangani KDRT,” simpul Singh. “Perjuangan kami masih jauh.” (Aljazeera)
Editor: Kristianto Galuwo