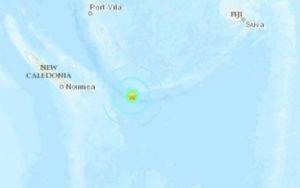Papua No.1 News Portal | Jubi
Oleh Leni Ma’ia’i
Aula besar di ibu kota Tonga, Nuku’alofa, sudah lama tidak dikunjungi begitu banyak orang sejak pembatasan akibat Covid-19 diberlakukan setahun yang lalu.
Namun pada Kamis malam (6/5/2021), orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat memadati setiap inci yang tersedia di gedung tersebut, kebanyakan berpakaian hitam dan gaun ta’ovala hasil tenunan tradisional.
Otoritas Tonga telah sepakat untuk memberlakukan pengecualian atas peraturan yang membatasi 50 orang untuk pertemuan yang diadakan di dalam ruangan, sehingga orang-orang dari seluruh bangsa di Pasifik itu dapat berhimpun bersama-sama dan menyalakan lilin, mengenang aktivis LGBTQ+ dan kemanusiaan, Polikalepo ‘Poli’ Kefu.
Kefu, 41 tahun, seorang tokoh yang dikagumi di Tonga. Ia tewas pada Sabtu pekan lalu di pantai di dekat rumahnya di Lapaha. Pihak kepolisian telah mendakwa seorang laki-laki berusia 27 tahun atas pembunuhannya. Kematian Kefu mengejutkan negara kecil itu dan komunitas LGBTQI+-nya, yang berharap peristiwa itu akan menyebabkan tindak tegas dalam mengatasi sikap homofobia dan mencabut UU diskriminatif di negara tersebut.
Salah satu orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhirnya adalah anggota keluarga kerajaan Tonga, Putri Frederica Tuita, yang berusaha untuk menahan tangisannya ketika dia berbicara tentang teman dekatnya selama hampir 20 tahun.
“Menjadi orang Tonga itu berarti hidup seperti Poli, mewujudkan nilai-nilai masyarakat kita yaitu kasih, kerendahan hati, rasa hormat, dan kesetiaan,” tutur Tuita.
Berupaya untuk diplomatis, mengingat posisinya yang tinggi, Putri Tuita melanjutkan dengan penyesalan akan Tonga karena membiarkan kematian Kefu terjadi.
“Masyarakat kita belum mengambil tanggung jawab yang diperlukan untuk benar-benar berkomitmen pada nilai-nilai Tonga itu, dan menerapkannya dalam hal-hal yang penting.”
Hal yang penting, Putri Tuita menyiratkan, adalah dalam hal memberikan perlindungan yang lebih baik bagi orang-orang leitī dari ancaman kejahatan kebencian atau hate crime.
Kata leitī dalam bahasa Tonga adalah salah satu dari banyak kata di seluruh wilayah Pasifik yang digunakan untuk mendeskripsikan ekspresi seksual dan gender yang beragam dalam negara mereka.
“Ini lebih merupakan kata sebutan untuk komunitas LGBTQ+. Kami menyebut semua orang leitī, baik mereka yang transgender, lesbian, atau apapun identifikasi diri Anda,” kata Joey Joleen Mataele, pendiri asosiasi Tonga Leitīs Association (TLA), yang menyerahkan jabatan kepresidenannya kepada Kefu pada 2018.
Seorang laki-laki telah menyerahkan dirinya ke polisi pada hari Senin ini dan kemudian didakwa dengan pembunuhan Kefu. Polisi Tonga belum mengumumkan pandangan mereka apakah Kefu adalah korban dari hate crime atau tidak.
Tagar #JusticeForPoli pun menjadi populer sementara komunitas-komunitas dari seluruh Pasifik Selatan berkumpul untuk mengadakan acara penyalaan lilin mereka sendiri. Secara khusus, keadilan yang didesak oleh kelompok-kelompok LGBTQ+ Pasifik adalah dalam hal reformasi hukum, termasuk pencabutan UU Pelanggaran Pidana Tonga, yang menetapkan aksi sodomi dapat dihukum hingga 10 tahun penjara.
Persoalan-persoalan hukum seperti ini tidak hanya terjadi di Tonga. Di negara-negara tujuan wisata populer seperti Samoa dan Kepulauan Cook, hubungan homoseksual dapat dihukum dengan hukuman penjara.
Samoa, yang telah menyelenggarakan kontes kecantikan fa’afafine – dipahami dalam istilah modern sebagai gender ketiga yang non biner – sejak tahun 1970-an, baru saja membatalkan UU yang mengkriminalkan ‘impersonasi’ perempuan pada tahun 2013.
Menurut Phylesha Brown-Acton, seorang perempuan fakafifine (sebutan identitas gender ketiga non biner di Niue) dan Direktur Eksekutif F’ine Pasifika, UU yang diskriminatif seperti itu telah memungkinkan beberapa anggota masyarakat untuk merasa dapat bertindak dengan cara-cara yang penuh kebencian terhadap orang-orang leitī.
“Ini seolah memberikan izin kepada orang-orang untuk semakin memperlakukan orang leitī lebih buruk daripada mereka memperlakukan anjing. Maaf untuk mengatakan ini, tetapi di Tonga, Tonga punya UU tentang Anjing. Anjing harus punya dokter hewan. Sama sekali tidak ada untuk leitī, kami dipandang sebagai kelas yang lebih rendah dari hewan seperti anjing,” tegas Brown-Acton.
Ymania Brown, sekretaris dari International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA World), bekerja bahu membahu dengan kelompok-kelompok LGBTQ+ di kawasan Pasifik untuk membantu memperjuangkan reformasi hukum yang diskriminatif.
“Ada banyak sekali faktor agar dapat berhasil mengubah hukum, dan beberapa faktor tersebut mencakup sikap budaya dari berbagai negara, yang juga berbeda di antara negara-negara di Pasifik. Mengetahui apa yang benar untuk Papua Nugini, mungkin tidak tepat untuk Kepulauan Solomon, atau untuk Tonga, atau Samoa,” jelas Brown.
Polisi cenderung menyalahkan korban
Polisi di sebagian besar negara Pasifik tidak secara khusus mencatat insiden hate crime, jadi sulit untuk mendapatkan data tentang seberapa sering kasus ini terjadi, tetapi Brown-Acton punya kisahnya sendiri yang menakutkan tentang betapa buruknya keadaan bagi mereka.
Dia mengatakan pada tahun 2007 dia adalah korban percobaan pemerkosaan beramai-ramai oleh sekitar 10 laki-laki. Menurutnya mereka menahan badannya sementara mencoba melepaskan celananya, tetapi dia berhasil bebas dan lari mencari bantuan. Brown-Acton lalu segera mengunjungi polisi untuk mengajukan tuntutan, tetapi mengatakan keluhannya tidak ditanggapi dengan serius.
“Pada dasarnya tanggapan polisi hanya seperti ini, ‘ini salahmu, kamu seharusnya tidak pernah kesana.’ Tidak ada apa-apa yang terjadi. Tidak ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban,” tegas Brown-Acton. Dia yakin dia diserang karena dia adalah leitī dan pihak polisi tidak menganggapnya serius karena alasan yang sama.
“Saya bukan satu-satunya orang yang pernah mengalami ini, leitī menghadapi dan mengalami kekerasan, hari demi hari”
Wakil Komisaris Polisi Tonga, Tevita Vailea mengatakan dia tidak tahu secara khusus tentang kasus ini, tetapi mengundang Brown-Acton untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang insiden tersebut.
“Polisi Tonga telah banyak berupaya untuk mengembangkan kapasitas dan pengembangan polisi Tonga kami,” kata Vailea. “Dan sebagai bagian dari itu adalah memperlakukan semua orang dalam masyarakat kita dengan lebih adil dan setara. Jadi kami berusaha sebaik mungkin untuk mendorong semua korban kejahatan agar datang dan melaporkannya kepada kami.”
Berdasarkan informasi yang ada saat ini investigasi polisi atas kematian Poli telah dilakukan secara menyeluruh dan efisien. Terdakwa pembunuh akan ditahan dan sudah dijadwalkan untuk hadir di hadapan pengadilan hakim pada 19 Mei. Investigasi atas kematiannya pun masih terus berlangsung.
Gereja bisa membantu perjuangan
Di luar kepolisian, Brown-Acton menerangkan bahwa hubungan yang rumit antara negara-negara Kepulauan Pasifik dan komunitas LGBTQ+ mereka sebagian besar dimulai dari masuknya agama Kristen ke Pasifik Selatan sejak abad ke-18.
Sebelum misionaris tiba di Pasifik, semua budaya Pasifik diketahui menerima orang-orang leitī, fa’afafine, dan banyak identitas seksual lainnya yang membentuk Pasifik.
Bagi lembaga-lembaga keagamaan, yang menjadi dasar kehidupan di Kepulauan Pasifik saat ini, proses untuk menerima praktik-praktik budaya ini memang panjang dan rumit.
Joey, pendiri TLA, dan seorang perempuan trans, mengenat kekagetan di wajah para jemaat ketika, di akhir tahun 1970-an, dia memberanikan diri untuk mengenakan gaun ketika menghadiri misa hari Minggu yang ramai. Sejauh yang dia tahu, dia adalah leitī pertama yang melakukannya di Tonga.
Saat ini, leitī di Tonga umumnya bebas untuk berpakaian sesuka mereka di gereja, dan mereka melihat pengakuan dari sejumlah lembaga keagamaan.
Pada acara kedukaan Kefu, Kardinal Soane Patita Paini Mafi, Uskup Katolik Roma di Tonga, berbicara tentang masyarakat yang ‘berduka bersama-sama dengan asosiasi leitī’.
Ymania Brown, dari ILGA World, mengatakan bahwa meskipun mungkin ada kemajuan, perjuangan masih panjang.
“Kita perlu memenangkan dukungan dari gereja sebelum kita bisa menang di depan para reformis hukum, karena jika kita menang di depan para pendeta, mereka akan berdiri di depan kita. Mereka benar-benar akan membela kita, demi penyertaan kita,” tutur Brown.
Sementara itu, TLA dan berbagai kelompok LGBTQ+ lainnya sedang berjuang untuk segera mendorong reformasi sistem hukum.
“Sulit bagi saya untuk mengatakan bahwa, ‘ya, kematian Poli pasti akan menghasilkan perubahan besar-besaran’, karena banyak dari itu tergantung bukan pada kita, karena kita sudah siap, itu tergantung pada legislator dan anggota parlemen di Pasifik untuk membela dan berani. Mereka perlu cukup peduli dengan kemanusiaan untuk mengatakan, ‘ya, ini adalah sekelompok orang yang memerlukan perlindungan’, dan baru akan ada perubahan,” kata Brown. (The Guardian)
Leni Ma’ia’i adalah seorang jurnalis dan penerbit lepas, ia menetap di Selandia Baru.
Editor: Kristianto Galuwo