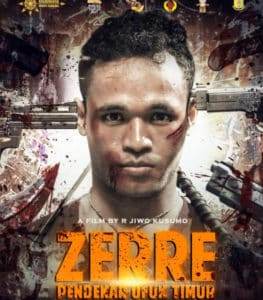Papua No. 1 News Portal | Jubi
Setiap detik nyawa manusia melayang/diculik dan dibunuh oleh penguasa/martabat ditilang/ korban bergantian tiada perhentian…
Penggalan puisi itu dibacakan lantang oleh Vonny Aronggear, seorang penyair perempuan Papua. Judulnya “Martabat Ditilang” ditulis di Yogyakarta, 15 Mei 2017.
Puisi itu karya Manfred Kudiai. Terbukukan dikumpulan puisinya yang perdana; “Jalan Pemberontak”. Diluncurkan di dunia maya lewat kanal Youtube pribadi Aprila Wayar, jurnalis dan seorang novelis perempuan Papua. Peluncuran bukunya pada Jumat sore, 26 Februari 2021 itu jadi istimewa. Karena diantar oleh penyair kenamaan Indonesia dari Yogyakarta; Joko Pinurbo.
Manfred adalah anak muda dari Paniai. Dia lahir di Wopa, 15 Maret 1994.
Sebelum memberi pengantar pada diskusi peluncuran buku itu, Joko Pinurbo atau Jokpin terlebih dahulu mengutip penggalan awal puisi Chairil Anwar yang terkenal berjudul “Isa” (1943); itu tubuh mengucur darah/ mengucur darah/rubuh patah/ mendampar tanya; aku salah?
Jokpin mengutip puisi Chairil Anwar, untuk menjelaskan isi buku puisi Manfred. Dalam puisi Chairil Anwar itu, jelas tergambar yang menderita di kayu salib adalah tubuh Yesus Kristus.
“Tubuh di sini bisa dimaknai lain.Saya membayangkan, tubuh yang mengucur darah, adalah tubuh Kristus dalam bentuk lain, yaitu tubuh Papua. Kumpulan puisi Manfred melukiskan betapa kondisi Papua seperti tubuh Kristus yanhg mengucur darah penuh penderitaan di kayu salib, itu intisari puisi Manfred yang bisa saya serap dengan perbandingan Chairil Anwar,” ujarnya.
Sebagai pengikut Kristus,lanjut Jokpin, tampak sekali Manfred tidak ingin menyerah kepada penderitaan dan kekalahan, puisinya menggambarkan semangat. Bukan hanya perlawanan. Tapi pemberontakan terhadap sistem kekuasaan yang membuat bangsa Papua kehilangan harkat dan martabatnya sendiri.
“Saya tidak ingin menggunakan terminologi politik dalam menyelami puisi Manfred. Puisinya merupakan manisfestasi dari penghayatannya sebagai Kristiani, bahwa jalan yang penuh dengan duri dan penderitaan, tidak boleh membuat kita menyerah dan kehilangan harapan.”
Untuk itu dia mengaku bahagia. Anak muda seperti Manfred masih percaya pada kekuatan dan daya magis puisi. Puisi tidak bisa mengubah situasi dan kondisi masyarakat. Tapi menurutnya puisi bisa menginspirasi orang orang.
Dia mencontohkan satu peristiwa ikonik pada acara pelantikan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden baru-baru ini. Pada momentum bersejarah itu, seorang penyair remaja berkulit hitam bernama Amanda Gorman, membaca puisinya “The Hill We Climb.” Puisi itu merupakan gugatannya terhadap pertikaian politik di AS,masih kuatnya politik identitas, rasisme di negara yang dianggap demokasinya paling maju. Puisi Amanda mengejutkan dunia, menyadarkan betapa puisi bisa jadi bahasa perjuangan.
“Apa yang dilakukan Amanda (di Amerika Serikat) dilakukan Manfred (di Papua), menyuarakan pemberontakan, tapi satu pihak jadi sarana pematangan iman yang penuh tantangan dan harus diperjuangkan,” ujarnya.
Karena itu menurutnya, kumpulan puisi Manfred tak sekadar berkisar pada urusan estetika dan literal. Tapi merupakan pernyataan politik. Lebih dari itu, juga merupakan sebuah kesaksisan iman yang diikuti dengan tanggung jawab sosial terhadap situasi di Papua.
Sementara itu, Vonny Aronggear yang turut menjadi pembicara menambahkan, selain bersuara keras di satu sisi, puisi Manfred di sisi lain seperti melagukan cinta terjadap Tuhannya, ibu atau mamanya. Itu bukan hanya semata hubungan itu fisik, mama dipuisinya dapat diartikan tanah Papua.
“Anak muda (Papua) menulis sangat sedikit, tidak banyak. Kayaknya menulis itu tidak sama mempesona seperti ketika kita bicara sepak bola. Saya beri apresiasi besar, untuk anak muda yang menyumbangkan literasi Papua,” ujar penyair perempuan yang juga dikenal aktif menyuarakan isu lingkungan di Papua itu.
Baca Juga:Manfred Kudiai luncurkan antologi puisinya, “Jalan Pemberontak”
Aprila Wayar yang memandu diskusi juga menambahkan sebuah amsal; menunggu penulis Papua lahir,sama seperti menunggu datangnya nabi. Saking sedikit dan lamanya.
Buku “Jalan Pemberontak” karya Manfred Kudiai memuat 51 puisi. Tebalnya 65 halaman. Diterbitkan Apro Publisher, Yogyakarta.
Aprila dalam pengantar di buku itu menulis, ada banyak realitas yang tidak dapat dituliskan secara gamblang dalam narasi jurnalistik. Mungkin ini salah satu alasan Manfred Kudiai, jurnalis muda Papua, memilih puisi sebagai jalan keluar atas masalah-masalah Papua yang demikian kompleks. Dia berharap kesadaran kritis generasi baru (Papua) akan lahir setekah membaca puisi-puisi Manfred Kudiai.
Manfred sendiri mengaku, belajar menulis puisi secara otodidak. Tanpa guru pembimbing. Dia mulai menulis puisi ketika menjadi mahasiswa tingkat awal di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, 2015 silam. Tapi minat menulisnya mulai tumbuh sejak di bangku SMK. Mula-mula sekadar catatan pengalaman pribadi. Dia juga belajar membuat karya jurnalistik. Tak heran meski belajar teknik mesin. Dia memilih profesi menjadi jurnalis. Dia menjadi pemimpin redaksi situs kabarmapegaa.com yang berbasis di Nabire.
“Jalan Pemberontak” lahir karena pikiran saya terpenjara banyak hal.Saya tidak bisa membiarkan pikiran saya untuk berekspresi. saya membenrontak semua yang menjadi pemalang pemikiran saya,” ujar pria yang gandrung dengan puisi Widji Tukul dan Kahlil Gibran ini.
Dia rela menyambi jadi pengemudi ojek, untuk tambah-tambah ongkos cetak buku puisinya. “Enam bulan saya jadi tukang ojek.”
Di penghujung acara peluncuran buku puisinya itu, Jokpin membacakan satu puisi Manfred yang menurutnya paling subtil, indah dan matang. Punya diksi segar dan mengejutkan.
“Saya sampai cemburu, kenapa bukan saya yang menulis puisi ini, kenapa Manfred yang menuliskannya,” ujarnya terkekeh.
Puisi itu berjudul “Ingin Pulang”:
Rindu terkoneksi dengan dunia asing,
di tanah kelahiranku
ketika kesepian menjadi minoritas
seperti terjerat dalam lingkaran tanah terlarang
ada tembok tak terlihat
karena hanya perbedaan pendapat
mulai mengangggu kedamaian
tidak menjadi bagian dari kehidupan,
mencari koneksi yang kudamba
pantang menyerah gapai cita cita
transformasi menyeruak reformasi bergulir di kota kota besar
berita kematian cenderawasih dan mambruk diabaikan
kematian seekor anjing menjadi headline di surat kabar
aku tidak mau lagi menjadi anak patuh yang sekadar menyenangkan diri
aku ingin menemukan jati diri
sebab aku tergeletak di dua perangkat kalimat nyaman dan tidak nyaman
berada di rumah yang dijaga anjing
aku ingin pulang, (*)