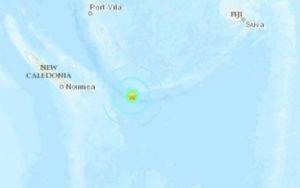Papua No.1 News Portal | Jubi
Oleh Thomas Tarurongo Wynne
E toketoke enua i runga i te papa enua. I teia nei, te totoro nei au ki roto I te tumu Enua,Te opu nei au i toku reo. Te kapu nei au i toku kapua,anga. Te mou nei au toku ui tupuna. Te tu nei au ki runga toku paepae.
Itu adalah kata-kata yang saya tulis, dan telah diterjemahkan oleh mama saya, ketika saya mencoba mencurahkan isi hati dan pikiran saya saat saya pindah ke Rarotonga pada tahun 2011.
Toketoke enua, perumpamaan tentang cacing tanah di atas, cacing itu masuk dari permukaan bumi, menggali semakin dalam ke dalam tanah, dan turun begitu jauh ke dalam bumi sehingga menjadi satu dengan bumi.
Dan dalam perjalanan itu menangkap reo (bahasa), memahami siapa tupuna (nenek moyang) kita, dan berdiri di atas paepae (halaman) seseorang, tempat darimana dirinya berasalnya.
Tidak ada satu pun dari semua pengalaman dan ilmu berharga ini bisa saya capai atau pahami jika saya tidak pindah dan tinggal di Ipukarea (rumah leluhur) kami. Dan rasa hubungan yang dalam seperti ini yang sangat saya rindukan, saat saya bekerja dan tinggal di sini, dan saya jadi nanti-nantikan saat kami pulang.
Meskipun demikian, jauh lebih berarti bagi saya untuk berada saat ini sambil memiliki perasaan yang lebih dalam bahwa saya mengetahui siapa identitas saya, dengan siapa saya terhubung dan di mana posisi saya di dunia yang terus berubah dan pasca-Covid ini.
Jika ada satu hal yang dirindukan orang-orang kami dari Kepulauan Cook yang lahir di Selandia Baru ini – sekarang 60 % dari 82.000 orang Kepulauan Cook ada di Aotearoa – itu adalah rasa keterikatan yang lebih dalam dengan tanah air kami.
Perasaan bahwa kita itu memiliki hubungan dengan sesuatu yang sesuai dengan identitas kita, sesuatu yang membuat kita unik, dan yang memberi kita rasa keaslian dan identitas yang lebih dalam. Dan jika ada satu hal yang dapat dipahami lebih baik oleh kita di rumah-rumah, saya yakin, adalah bagaimana kita juga terhubung dengan sumber daya manusia yaitu orang-orang kita, dan melengkapi ipukarea (rumah leluhur) kita dengan keterampilan yang telah mereka peroleh selama berada di Aotearoa.
Depopulasi Kepulauan Cook itu merupakan isu yang banyak dibahas akhir-akhir ini dan hati saya sedih membaca komentar-komentar daring tentang banyaknya orang-orang Kepulauan Cook yang pergi merantau untuk mendapatkan gaji yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, dan keamanan.
Tapi ini bukanlah hal baru; faktanya adalah orang-orang Kepulauan Cook sudah mulai pergi meninggalkan rumah kami dengan pelan tapi pasti selama 50 tahun terakhir. Hal ini lalu dipercepat oleh adanya Bandara Internasional yang dibangun pada tahun 1973, krisis ekonomi tahun 1996, dan sekarang terjadinya pandemi global.
Dan saya tidak pernah menemukan pemerintah manapun selama bertahun-tahun ini, yang dengan sengaja berencana, dan dengan mempertimbangkan jumlah tertentu, untuk memberikan insentif kepada orang-orang kami agar kembali ke rumah.
Isu depopulasi sudah ada diam-diam di bawah permukaan, sebuah ketimpangan yang diam-diam ditutupi oleh lebih dari tiga ribu pekerja asing di Rarotonga. Dan menurut pandangan saya, kami itu tidak jujur jika kami mengatakan bahwa Covid-19 menciptakan masalah ini. Satu-satunya hal yang terjadi akibat Covid-19, seperti yang telah pandemi itu lakukan semua di seluruh dunia, adalah menyingkapkan sebuah isu yang sudah lama ada.
Dalam sebuah tulisan berjudul ‘The politics of association: a comparative analysis of New Zealand and United States approaches to free association with Pacific island states’, penulis John Henderson menekankan bahwa memang benar, depopulasi mungkin merupakan warisan paling menghancurkan yang ditinggalkan oleh hubungan antara Selandia Baru dengan Kepulauan Cook.
Henderson mencatat hal yang sama tidak terjadi dengan hasil yang sama tingginya di negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya karena hanya penduduk Kepulauan Cook dan Niue yang memiliki hak otomatis, sebagai warga negara Selandia Baru, untuk memasuki Selandia Baru.
Tetapi privilese ini, kecemburuan yang dirasakan pulau-pulau Pasifik lainnya, Henderson menyimpulkan, mungkin akan berubah menjadi sebuah kutukan karena konsekuensinya yang dapat mempengaruhi kelangsungan masa depan Kepulauan Cook dan Niue.
Dia menambahkan bahwa banyaknya rumah-rumah masyarakat yang kosong saat ini telah menjadi ciri khas dari setiap desa di Niue (dan daerah terluar Kepulauan Cook), atau sekolah-sekolah yang digabungkan adalah bukti nyata dari apa yang disebut sebagai negara yang ‘kosong’.
Depopulasi, menyelesaikan isu upah minimum rendah, atau ketergantungan pada satu sumber pemasukan dari sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan nasional, ini semua bukanlah persoalan-persoalan yang baru.
Pemerintah yang dengan penuh keborosan membelanjakan uang untuk diri mereka sendiri sambil meminta masyarakat untuk menahan diri juga bukanlah hal baru, begitu pula nepotisme dimana orang-orang dipekerjakan untuk memegang jabatan tertentu padahal kapasitas mereka kecil, atau dipecat karena berani angkat suara.
Bukan Covid-19 yang menyebabkan orang-orang kita pergi; pandemi itu hanya membawa persoalan-persoalan ini ke permukaan dan dengan pasti menunjukkan sejumlah persoalan mendesak yang membuat hingga orang-orang kami tidak kembali ke rumah.
Sayangnya, pada akhirnya, kedua pihak tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka yang berada di Selandia Baru karena mereka tidak dapat, seperti perumpamaan toketoke tadi, menggali jauh ke dalam bumi Ipukarea kami untuk mencari harta karun yang ada di sana. Sementara mereka yang ada di rumah, yang memerlukan orang-orang kami untuk kembali dan menaikkan populasi dan menyelesaikan isu keterbatasan SDM setempat kita.
Apa pun sisi masalah yang kita bela, yang pasti adalah kita sangat membutuhkan perubahan. Dan meskipun perubahan yang bermakna adalah sesuatu yang susah untuk dicapai, pemilu di Samoa jelas menunjukkan bahwa pada akhirnya masyarakat akan mencapai titik dimana mereka merasa muak. (Cook Islands News)
Thomas Tarurongo Wynne adalah mantan penasihat pemerintah Kepulauan Cook dan sekarang menetap di Wellington.
Editor: Kristianto Galuwo